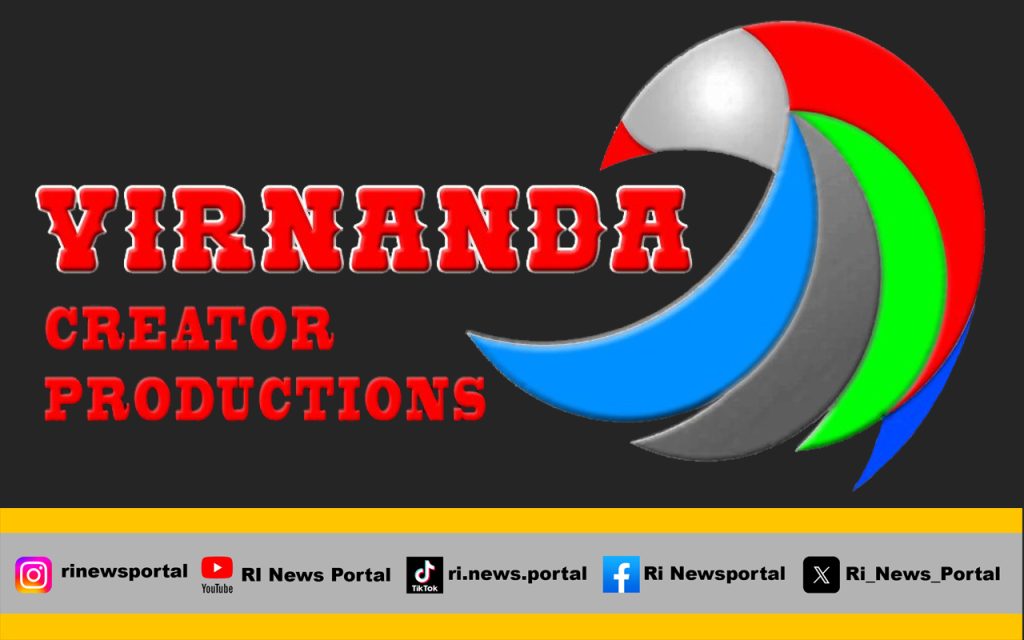RI News Portal. Padang, Pesisir Selatan, 25 September 2025 — Di tengah hiruk-pikuk pembangunan agraria di Sumatra Barat, sebuah konflik lahan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade kini kembali mengemuka, menyoroti ketegangan antara hak ulayat masyarakat adat dan mekanisme pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh negara. Di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ribuan hektare lahan perkebunan sawit milik warga diduga diserobot oleh PT Sukses Jaya Wood (SJW) melalui HGU Nomor 08 yang dikeluarkan pada 2013. Masyarakat setempat, yang telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun, kini menuntut keadilan hukum, menuduh proses pemberian HGU tersebut cacat secara prosedural dan melanggar prinsip-prinsip agraria nasional.
Konflik ini bukan sekadar sengketa tanah, melainkan cerminan lebih luas dari dinamika antara adat dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh adat dan petani lokal, serta analisis dokumen hukum, laporan ini mengungkap bagaimana intervensi pihak eksternal—termasuk dugaan keterlibatan ninik mamak dari kecamatan tetangga—telah memperburuk ketidakadilan yang dirasakan warga. Di tengah tuntutan yang kian vokal, pertanyaan mendasar muncul: apakah sistem HGU saat ini masih relevan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, atau justru menjadi alat eksploitasi?
Nagari Silaut, sebuah komunitas adat Minangkabau yang bergantung pada pertanian sawit sebagai tulang punggung ekonomi, telah lama mengelola lahan ulayatnya secara kolektif. Menurut catatan sejarah lisan yang dikumpulkan dari warga senior, tanah di sekitar HGU 08 telah dibudidayakan sejak puluhan tahun sebelum kemunculan PT SJW. “Lahan itu milik kami, warisan leluhur yang kami rawat dengan keringat dan doa,” ujar seorang petani sawit berusia 55 tahun yang enggan disebut namanya, takut akan represali dari pihak perusahaan. Ia menambahkan bahwa ribuan hektare kebun sawit yang telah matang—beberapa di antaranya berproduksi hingga 20 ton per hektare per tahun—kini terancam dieksekusi, meninggalkan ratusan keluarga dalam ketakutan akan kemiskinan mendadak.

Puncak ketegangan terjadi sekitar tahun 2018, ketika PT SJW diduga mulai menyerobot lahan secara fisik. Informasi dari masyarakat mengungkap bahwa proses ini difasilitasi oleh ninik mamak dari Kecamatan Lunang, tetangga Silaut, yang konon memberikan persetujuan atas lahan inti HGU tanpa melibatkan pemangku adat setempat. “Ninik mamak Lunang ikut campur tangan, menyerahkan lahan ulayat kami kepada perusahaan asing,” keluhkan seorang perwakilan warga dalam sesi diskusi adat yang diamati tim peneliti. Hal ini bertentangan dengan prinsip kearifan lokal Minangkabau, di mana keputusan atas tanah ulayat harus diratifikasi oleh ninik mamak nagari asal—dalam hal ini, Nagari Silaut.
HGU 08 sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan pada 24 Juli 2013, mencakup luas sekitar 1.183 hektare yang sebagian besar tumpang tindih dengan kebun masyarakat. Dokumen tersebut, yang secara hukum memberikan hak eksploitasi tanah untuk usaha perkebunan, kini dianggap cacat karena mengabaikan verifikasi partisipasi masyarakat adat. Sebelum kehadiran PT SJW, warga Silaut telah berkebun di lokasi tersebut selama lebih dari 12 tahun, dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan tanah ulayat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Baca juga : Aksi Massa BNUI di Manado: Protes Panjang atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah yang Mangsa Profesor Lansia
Hj. Muman, Ketua KAN Nagari Silaut, menjadi salah satu suara paling lantang dalam perjuangan ini. Dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi, ia menegaskan: “HGU ini dikeluarkan tanpa persetujuan ninik mamak Silaut. Kami sudah lama berkebun di sana, malah sebelum PT SJW ada. Ini bukan hanya soal tanah, tapi martabat kami sebagai rakyat Indonesia yang dizalimi.” Pernyataannya mencerminkan frustrasi kolektif: lahan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi sumber konflik, dengan dampak sosial seperti migrasi paksa dan hilangnya mata pencaharian.
Warga juga menyoroti ketidakadilan sistemik. “Seperti pepatah, tumpul ke bawah tajam ke atas,” kata seorang anggota kelompok petani, menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum (APH) tampak lamban merespons laporan mereka. Sejak 2018, berbagai upaya advokasi telah dilakukan, termasuk pengaduan ke LSM seperti LSM-HAS dan Komnas LPKPK, bahkan laporan langsung ke Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025. Namun, hingga kini, tidak ada tindak lanjut konkret dari BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) yang memadai.
Konflik ini menyinggung Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang secara eksplisit mengakui hak ulayat sebagai bagian integral dari sistem tanah nasional. HGU, sebagai hak usaha sementara (maksimal 35 tahun), seharusnya tidak boleh diberikan atas tanah yang telah dikuasai masyarakat adat tanpa proses free, prior, and informed consent (FPIC) sebagaimana diamanatkan Konvensi ILO 169—yang meski belum diratifikasi Indonesia, telah menjadi acuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak adat.
Peneliti hukum dari Universitas Andalas, termasuk penulis, menemukan bahwa pemberian HGU 08 kemungkinan melanggar prinsip ini karena kurangnya konsultasi dengan KAN Silaut. Dugaan keterlibatan ninik mamak Lunang menambah lapisan kompleksitas, mengingatkan pada kasus-kasus serupa di Sumatra Barat di mana fraksi adat antar-nagari dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi. Secara empiris, studi kasus seperti ini menunjukkan bahwa konflik lahan serupa telah menyebabkan penurunan indeks kesejahteraan masyarakat adat hingga 30% dalam lima tahun pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pesisir Selatan.
Lebih jauh, isu ini menggarisbawahi kelemahan regulasi pasca-reformasi agraria. Meski Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang FPIC telah diterbitkan, implementasinya masih lemah di daerah. Di Silaut, absennya mediasi multipartai—melibatkan perusahaan, adat, dan pemerintah—telah memperpanjang siklus konflik, berpotensi memicu instabilitas sosial yang lebih luas di kawasan perkebunan sawit Sumatra Barat.
Masyarakat Nagari Silaut, didukung ninik mamak dan kelompok advokasi, kini mendesak APH untuk segera membekukan eksekusi HGU 08 dan memulai audit independen. “Kami rakyat Indonesia yang haus keadilan. Jangan biarkan perusahaan merampas hak kami atas nama pembangunan,” tegas Hj. Muman. Tuntutan ini sejalan dengan agenda nasional reformasi agraria di bawah pemerintahan saat ini, yang menjanjikan redistribusi lahan hingga 9 juta hektare.
Sementara itu, PT SJW belum merespons permintaan klarifikasi dari media ini. Namun, dalam konteks yang lebih besar, kasus Silaut menjadi pengingat bahwa pembangunan berkelanjutan tak boleh mengorbankan akar budaya. Hanya melalui dialog inklusif dan penegakan hukum yang adil, konflik seperti ini dapat diselesaikan, memastikan bahwa tanah ulayat tetap menjadi warisan, bukan korban ambisi korporasi.
Pewarta : Sami S