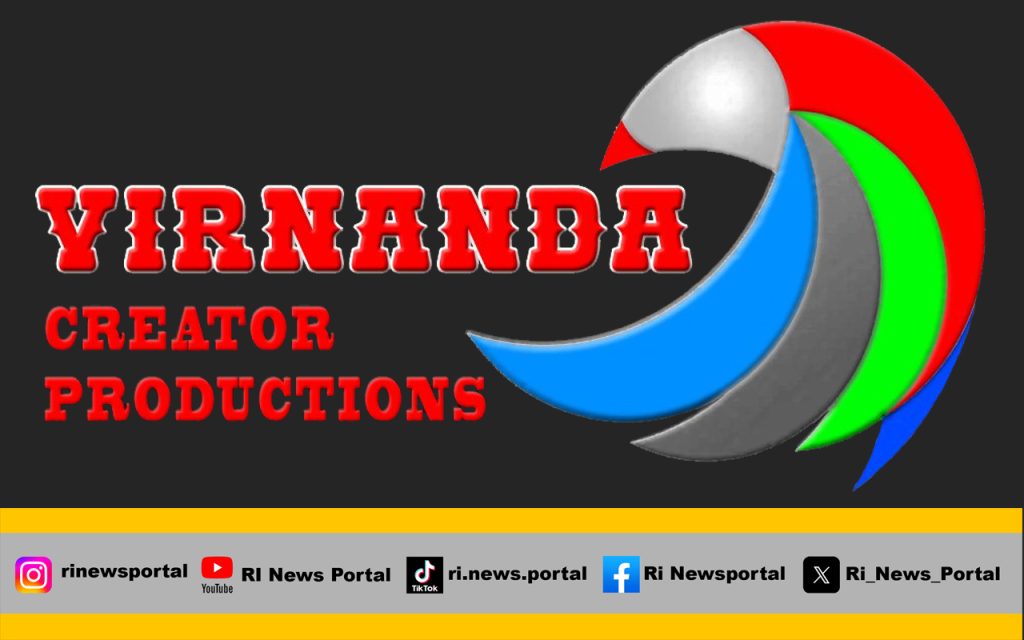RI News Portal. Semarang, 14 September 2025 – Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, sekelompok perwakilan warga Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, mengambil langkah berani dengan mendatangi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah di Jalan Gedungbatu Timur No. 129, Simongan, Semarang Barat, pada 13 September 2025. Kunjungan ini bukan sekadar aduan biasa, melainkan seruan mendesak untuk pendampingan media dalam menentang rencana pembangunan Gardu Induk PT PLN (Persero) yang diproyeksikan berdiri tepat di jantung permukiman desa mereka. Apa yang tampak sebagai konflik lokal ini sebenarnya mencerminkan pertarungan klasik antara kebutuhan infrastruktur nasional dan hak hidup masyarakat akar rumput, dengan implikasi hukum dan sosial yang mendalam.
Peristiwa ini dimulai dari keresahan warga yang telah berlarut-larut. Gardu Induk, yang direncanakan sebagai pusat distribusi listrik bertegangan tinggi, dianggap tidak pantas dibangun di kawasan padat penduduk. “Lokasi ini berada di tengah desa, dekat rumah-rumah warga, sekolah, dan lahan pertanian. Kami khawatir radiasi elektromagnetik, kebisingan, dan risiko kecelakaan seperti kebakaran atau ledakan akan mengancam nyawa kami sehari-hari,” ujar salah satu perwakilan warga, yang enggan disebut namanya karena alasan keamanan. Aspirasi penolakan ini bukan hal baru; surat resmi telah dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah, termasuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Jepara dan PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah, namun hingga kini responsnya nihil, seolah suara mereka lenyap dalam birokrasi yang rumit.

Kedatangan ke DPW IWOI Jawa Tengah menjadi strategi cerdas warga untuk memperluas jangkauan suara mereka. “Kami datang ke sini karena suara kami tidak didengar. Harapan kami, media bisa mengawal dan mendampingi perjuangan warga agar pembangunan gardu induk yang merugikan masyarakat ini bisa dibatalkan,” tambah perwakilan tersebut. Respons dari IWOI pun positif. Ketua DPW IWOI Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, langsung menyambut delegasi dengan komitmen tegas: “Kami akan mendampingi, menyuarakan, dan menyebarluaskan informasi ini agar publik mengetahui permasalahan yang terjadi. Suara rakyat tidak boleh diabaikan.” Pendekatan ini menyoroti peran media sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan, terutama di era digital di mana informasi bisa menyebar cepat melalui platform online.
Dari perspektif akademis, kasus ini menyentuh inti prinsip hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan di Indonesia, yang sering kali menjadi arena perebutan antara kepentingan negara dan hak masyarakat. Divisi Hukum DPW IWOI Jawa Tengah, Akhmad Dalhar, S.H., M.H., menyatakan siap mengkaji aspek legalitas: “Kami akan memeriksa legalitas perizinan, tata ruang, dan aturan perlindungan lahan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Jika ada pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.”
Secara spesifik, pembangunan Gardu Induk ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 36 undang-undang ini menekankan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izin yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika lokasi gardu induk tidak termasuk dalam zona infrastruktur energi dalam RTRW Kabupaten Jepara, maka pembangunan ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Lebih lanjut, Pasal 69 secara eksplisit melarang pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dengan sanksi administratif hingga pidana. Pasal 61 huruf c memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan, yang dalam kasus ini telah dilakukan melalui surat resmi, namun diabaikan—sebuah indikasi potensial kelalaian birokrasi yang bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan krusial. Pasal 22 mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap kegiatan yang berdampak penting, seperti gardu induk yang melibatkan medan elektromagnetik dan potensi pencemaran. Jika PLN melanjutkan tanpa AMDAL yang lengkap dan partisipatif—termasuk konsultasi publik—maka Pasal 109 bisa diterapkan, dengan ancaman pidana penjara 1-3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Kajian ini bukan sekadar teori; preseden seperti kasus pembangunan infrastruktur di daerah lain, misalnya penolakan gardu induk di Jawa Barat pada 2023, menunjukkan bahwa gugatan berbasis AMDAL sering berhasil membatalkan proyek jika terbukti mengabaikan hak masyarakat.
Dari sudut pandang hukum konstitusional, kasus ini juga menyentuh Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penempatan gardu induk di permukiman bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi spasial, di mana masyarakat pedesaan menjadi korban prioritas pembangunan nasional tanpa kompensasi yang adil.
Secara sosial, penolakan ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan cerminan ketidakadilan struktural di masyarakat pedesaan Indonesia. Dampak utama adalah erosi kepercayaan terhadap pemerintah dan korporasi negara seperti PLN. Warga Tunggul Pandean, yang mayoritas petani dan buruh harian, merasa aspirasi mereka diabaikan, yang bisa memicu konflik horizontal antarwarga—misalnya antara yang menolak dan yang mungkin mendukung proyek karena janji lapangan kerja. Efek psikologis pun tak kalah serius: kecemasan kronis atas risiko kesehatan, seperti paparan radiasi yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker menurut studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bisa menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Lebih luas, kasus ini memperkuat narasi ketimpangan regional. Jepara, sebagai kabupaten dengan potensi wisata dan pertanian, berisiko kehilangan identitas budaya jika infrastruktur industri merusak lingkungan. Efek domino sosial termasuk migrasi penduduk muda ke kota, meninggalkan desa yang semakin rentan. Namun, ada sisi positif: keterlibatan IWOI bisa mendorong pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum dan media sosial, mengubah keresahan menjadi gerakan advokasi yang lebih terorganisir. Ini sejalan dengan teori konflik sosial Karl Marx, di mana kelas bawah melawan dominasi kapital negara, potensial memicu reformasi kebijakan yang lebih inklusif.
Warga Tunggul Pandean kini menuntut pembatalan total proyek, dengan desakan agar pemerintah daerah, PLN, dan instansi terkait menghentikan aktivitas di lahan desa. Kehadiran IWOI diharapkan membuka dialog terbuka, memperkuat posisi hukum masyarakat, dan memberikan tekanan moral untuk mencabut rencana tersebut. Di era pasca-pandemi di mana ketahanan energi menjadi prioritas, pertanyaan besarnya adalah: apakah pembangunan harus selalu mengorbankan masyarakat kecil? Kasus ini bisa menjadi tonggak bagi advokasi lingkungan di Jawa Tengah, mengingatkan bahwa suara rakyat adalah pondasi demokrasi sejati.
Pewarta : Miftahkul Ma’na