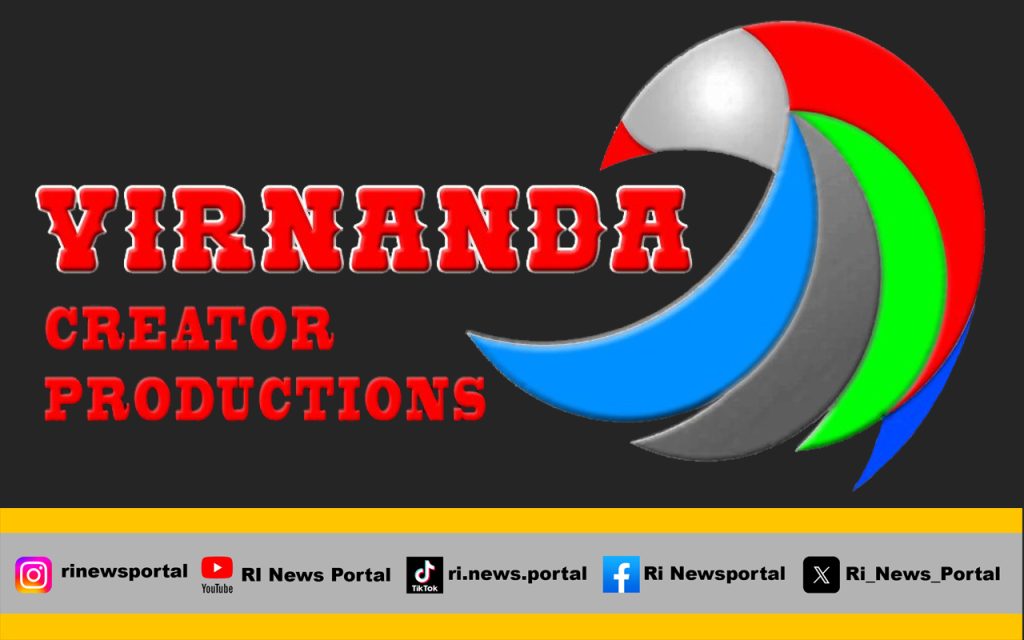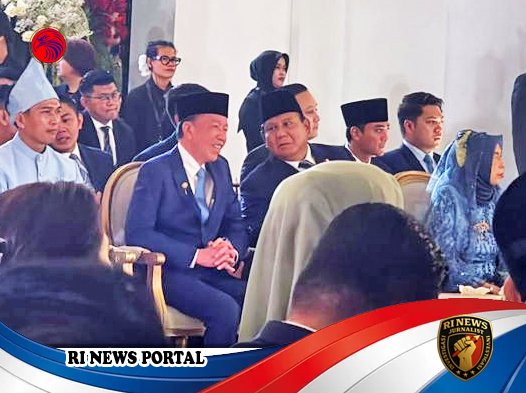RI News Portal. Semarang 1 Oktober 2025 – Di tengah hiruk-pikuk perubahan global yang semakin cepat, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Peringatan ini bukan hanya ritual tahunan yang sarat simbolisme, melainkan panggilan untuk merefleksikan ketahanan ideologi negara di tengah arus deras kapitalisme, digitalisasi, dan polarisasi internal. Berdasarkan sejarahnya, hari ini merujuk pada peristiwa tragis antara 30 September hingga 1 Oktober 1965, yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S), di mana upaya kudeta yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal, sehingga Pancasila tetap berdiri sebagai dasar negara. Namun, enam dekade kemudian, pertanyaan krusial muncul: Apakah Pancasila masih “sakti” di era ini, atau justru sedang diuji oleh dinamika baru yang lebih halus namun tak kalah mengancam?
Hari Kesaktian Pancasila secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 5 Oktober 1966, menyusul kegagalan upaya kudeta yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat. Narasi resmi Orde Baru menggambarkan peristiwa ini sebagai pemberontakan PKI yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis, sehingga Pancasila dianggap “sakti” karena berhasil mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perayaan ini awalnya hanya diperingati oleh kalangan militer, sebelum menjadi hari nasional yang menekankan Pancasila sebagai fondasi pemersatu masyarakat majemuk.

Namun, perspektif sejarah ini tidak luput dari kontroversi. Beberapa ahli dan korban peristiwa 1965-1966 memandang narasi resmi sebagai propaganda Orde Baru untuk membenarkan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Dokumen-dokumen seperti film propaganda “Pengkhianatan G30S/PKI” (1984) dianggap sebagai alat untuk memperkuat stigma anti-komunis, sementara penelitian internasional menunjukkan keterlibatan militer dan dukungan asing, termasuk dari Amerika Serikat, dalam pembantaian tersebut. Pandangan alternatif ini menekankan bahwa peristiwa tersebut bukan semata-mata pemberontakan PKI, melainkan konflik internal militer yang dieksploitasi untuk perebutan kekuasaan. Di era reformasi, diskusi ini semakin terbuka, meskipun stigma komunisme masih menghantui, seperti dalam perdebatan revisi KUHP yang mempertahankan pasal anti-komunisme.
Enam dekade pasca-1965, lanskap ideologi dunia telah bergeser drastis. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai akhir dominasi komunisme, digantikan oleh hegemoni kapitalisme pasar bebas, globalisasi budaya, dan penetrasi teknologi digital. Pancasila, yang terbukti “sakti” menghadapi ancaman ideologi asing selama Perang Dingin, kini dihadapkan pada tantangan baru: homogenisasi budaya melalui media sosial, ketimpangan ekonomi akibat neoliberalisme, dan erosi nilai tradisional oleh algoritma digital.
Baca juga : Inter Milan Dominasi Slavia Praha dengan Kemenangan 3-0 di Liga Champions
Para pakar menilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, keterbukaan global dengan kearifan lokal. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukan sekadar kompromi politik founding fathers, melainkan filosofi hidup yang mampu menjawab krisis kontemporer, seperti ketidakadilan sosial dan konflik identitas. Dalam konteks diplomatik, Pancasila selaras dengan Prinsip Bandung 1955, yang menekankan perdamaian dan kerjasama antar-negara berkembang, seperti dalam hubungan Indonesia-China yang menolak unilateralisme. Namun, implementasinya sering gagal: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih merajalela, sementara ketimpangan sosial-ekonomi melebar, menurut data Bank Dunia dan laporan lokal.
Di media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), peringatan tahun ini dirayakan dengan ucapan selamat dan refleksi, tapi juga kritik. Beberapa pengguna menolak “dogma” G30S/PKI sebagai narasi usang, sementara yang lain menekankan Pancasila sebagai “philosophische grounding” atau fondasi filsafat hidup. Diskusi ini mencerminkan polarisasi: dari upacara resmi di instansi pemerintah hingga perdebatan tentang Pancasila sebagai alat penguatan persatuan di era digital.

Tantangan terbesar Pancasila bukan lagi ideologi asing, melainkan praktik internal bangsa sendiri. Politik identitas, intoleransi agama, dan konflik etnis sering menantang semangat Bhinneka Tunggal Ika, seperti kasus-kasus kekerasan di berbagai daerah. Selain itu, globalisasi ekonomi telah menciptakan “enclave” yang terisolasi secara sosial, di mana dominasi etnis tertentu dan konglomerat global mengancam kedaulatan. Para analis menyoroti bahwa Pancasila harus diaktualisasikan sebagai benteng terhadap radikalisme, sekularisme berlebih, dan sosialisme-komunisme yang tersisa, sambil tetap fleksibel menghadapi perubahan.
Untuk menjaga kesaktiannya, diperlukan pendekatan holistik: pendidikan Pancasila yang tidak dogmatis, kebijakan ekonomi yang inklusif, dan dialog lintas generasi. Seperti disoroti dalam seminar UGM, Pancasila adalah cerminan budaya bangsa yang harus hidup dalam praktik sehari-hari, bukan hanya seremoni. Di tengah krisis kemanusiaan global, pidato Presiden Prabowo di PBB baru-baru ini menegaskan Pancasila sebagai role model diplomasi damai.
Pancasila tetap sakti jika diimplementasikan secara nyata. Di era global, kesaktiannya terletak pada kemampuan menyeimbangkan perubahan dengan identitas nasional. Namun, tanpa aksi konkret melawan korupsi dan ketimpangan, Pancasila berisiko menjadi slogan kosong. Peringatan hari ini harus menjadi momentum introspeksi, bukan hanya perayaan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, perekat bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
Pewarta : Setiawan Wibisono