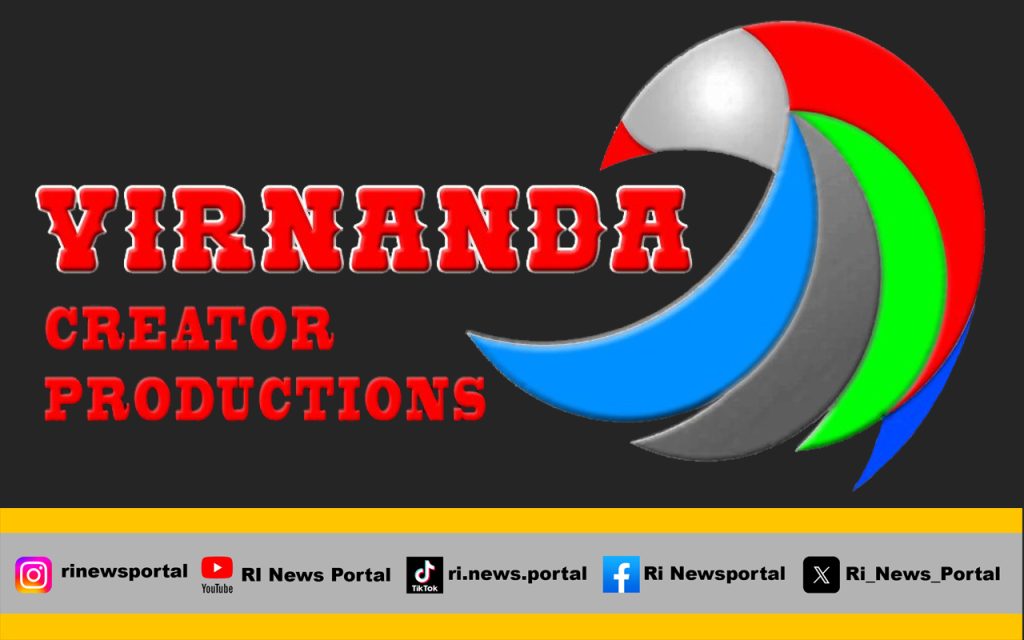RI News Portal. London 28 September 2025 – Insiden penahanan pemimpin Workers Party of Britain (Partai Buruh Inggris), George Galloway, beserta istrinya Putri Gayatri Pertiwi, di Bandara Gatwick London pada Sabtu (27/9/2025) telah memicu gelombang perdebatan sengit tentang batas antara penegakan keamanan nasional dan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Kejadian ini, yang terjadi tepat setelah keduanya kembali dari perjalanan ke Moskow via Abu Dhabi, menyoroti ketegangan geopolitik yang semakin rumit di era pasca-pandemi, di mana undang-undang antiterorisme menjadi alat ganda: pelindung sekaligus pedang bermata dua.
Galloway, 71 tahun, mantan anggota parlemen Inggris yang terkenal dengan sikap vokalnya terhadap isu Timur Tengah dan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Barat, diamankan oleh Komando Antiterorisme Kepolisian Metropolitan (Met Police). Istri ketiga Galloway, Gayatri, 43 tahun, yang berlatar belakang Indonesia dan dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dengan akar budaya Jawa, turut menjadi korban pemeriksaan ini. Menurut pernyataan resmi Met Police kepada Herald Scotland, “pada hari Sabtu, 27 September, petugas antiterorisme di Bandara Gatwick menghentikan seorang pria berusia 70-an dan seorang wanita berusia 40-an berdasarkan Lampiran 3 Undang-Undang Antiterorisme dan Keamanan Perbatasan 2019.” Keduanya tidak ditangkap secara formal, melainkan hanya ditahan sementara untuk interogasi, penggeledahan, dan pemeriksaan barang bawaan sebelum akhirnya dibebaskan dan melanjutkan perjalanan.
Partai yang dipimpin Galloway segera merespons melalui pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter). “Pukul 11 pagi kami diberitahu oleh petugas polisi di Gatwick bahwa pemimpin partai kami, George Galloway, dan istrinya telah ditahan di bandara,” tulis akun resmi partai, yang juga menandai akun polisi Sussex dan British Transport Police. Pernyataan itu melanjutkan dengan nada protes yang tegas: “Kami mengutuk upaya intimidasi terhadap mereka yang mencari persahabatan daripada permusuhan dengan dunia.” Chris Williamson, mantan anggota parlemen Labour yang kini bergabung dengan partai Galloway, menambahkan di X: “Apa yang sedang terjadi pada negara kita? Teman dan rekan saya ditahan seperti ini.” Respons ini mencerminkan narasi yang lebih luas dari kalangan sayap kiri Inggris, yang melihat insiden ini sebagai bagian dari pola penindasan terhadap suara disiden di tengah ketegangan global.

Untuk memahami konteks hukum, kita harus menyelami Lampiran 3 Undang-Undang Antiterorisme dan Keamanan Perbatasan 2019 (Counter-Terrorism and Border Security Act 2019). Undang-undang ini, yang lahir dari kekhawatiran pasca-Brexit tentang ancaman hibrida dari aktor negara asing, memberikan wewenang luar biasa kepada petugas perbatasan. Seperti dijelaskan dalam laporan Komisioner Kekuasaan Investigasi (Independent Reviewer of Terrorism Legislation, IRTL) Inggris, jadwal ini memungkinkan polisi untuk “menghentikan, menginterogasi, menggeledah, dan menahan seseorang di pintu kedatangan Inggris guna menentukan apakah mereka terlibat dalam aktivitas permusuhan.” Aktivitas permusuhan di sini didefinisikan secara luas, mencakup dukungan terhadap kelompok teroris, spionase, atau bahkan perjalanan ke wilayah konflik yang dianggap sensitif—seperti Rusia, yang saat ini menjadi target sanksi Barat akibat invasi Ukraina.
Lebih lanjut, laporan IRTL menekankan bahwa wewenang ini juga mencakup penyitaan, penyalinan, penggunaan, dan bahkan pemusnahan barang bawaan jika dianggap mengandung materi rahasia. “Komisioner Kekuasaan Investigasi dapat mengizinkan penyimpanan dan penggunaan salinan barang, termasuk yang berisi informasi sensitif,” tulis dokumen tersebut. Pengawasan dilakukan oleh IRTL, yang bertugas meninjau dan melaporkan pelaksanaan undang-undang ini secara berkala. Namun, kritik dari pakar hukum seperti Dr. Conor McGale dari University of Glasgow menyoroti celah: “Wewenang ini bersifat preventif dan reaktif, tapi kurang transparan. Tanpa bukti konkret, pemeriksaan seperti ini bisa menjadi alat untuk membungkam aktivis politik, terutama yang kritis terhadap NATO atau kebijakan Israel.”
Baca juga : Lavrov di Sidang PBB: Ancaman Barat dan Pintu Negosiasi Rusia yang Terbuka
Dalam kasus Galloway, latar belakang perjalanannya ke Moskow menjadi sorotan utama. Sebagai politisi yang pernah memenangkan kursi Rochdale pada pemilu sela 2024 dengan kampanye anti-perang Gaza, Galloway dikenal dekat dengan narasi Rusia melalui wawancara di RT (Russia Today). Perjalanan ini, yang diduga terkait diskusi diplomatik independen, mungkin memicu alarm otomatis di sistem intelijen perbatasan. Sementara itu, Gayatri—yang lahir di Jakarta dan pindah ke Inggris pada 2012—membawa dimensi pribadi yang menarik. Sebagai penulis buku tentang feminisme Islam dan keturunan Jawa, ia sering mendampingi suaminya dalam advokasi hak Palestina, yang membuatnya rentan terhadap stereotip “ancaman asing” di mata otoritas Barat.
Insiden ini bukanlah yang pertama bagi figur seperti Galloway. Sejarahnya sebagai ketua Partai Respect yang bubar pada 2016 dan pendirinya Workers Party pada 2019 menunjukkan pola: ia sering menjadi target karena pandangannya yang pro-Palestina dan anti-imperialisme. Baru Agustus lalu, ia mengumumkan niat maju di pemilu parlemen Skotlandia 2026, dengan Yvonne Ridley—jurnalis mantan anggota Alba Party—sebagai calon pendamping di Glasgow Pollok. Penahanan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengganggu momentum politiknya, terutama di tengah polarisasi pasca-kemenangan Keir Starmer di pemilu 2024.

Dari perspektif akademis, kejadian ini menggambarkan dinamika “keamanan sekuritisasi” dalam teori hubungan internasional, di mana isu politik diubah menjadi ancaman keamanan untuk membenarkan intervensi negara. Seperti yang dianalisis oleh profesor Barry Buzan dalam kerangka Copenhagen School, proses ini sering kali menargetkan minoritas atau disiden, termasuk komunitas diaspora seperti Gayatri yang mewakili suara Asia Tenggara di panggung global. Di Indonesia, di mana Gayatri masih memiliki ikatan keluarga, insiden ini berpotensi memicu diskusi tentang hak diaspora dan perlindungan warga negara ganda di bawah konvensi internasional.
Hingga kini, Galloway belum memberikan komentar pribadi, tapi partainya menjanjikan tindak lanjut hukum. “Ini adalah intimidasi politik yang telanjang,” tegas juru bicara partai. Sementara Met Police menolak spekulasi lebih lanjut, kejadian ini mengingatkan kita pada esensi demokrasi: apakah kebebasan bergerak dan berpendapat harus dikorbankan demi “keamanan”? Di era di mana perbatasan digital dan fisik saling tumpang tindih, jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan hak sipil di Inggris—and beyond.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH