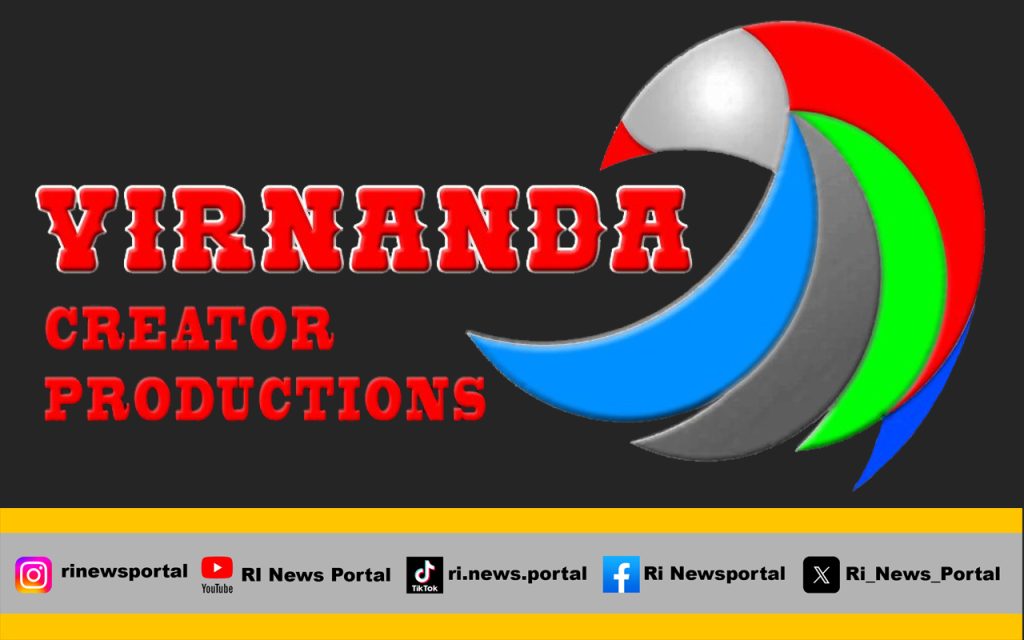RI News Portal. Beirut, 14 November 2025 – Hampir setahun setelah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon mulai berlaku, laporan terbaru dari Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mengungkapkan pola pelanggaran yang sistematis, dengan korban jiwa sipil mencapai 114 orang sejak November 2024. Data ini, yang dirilis pada Kamis (13/11), menyoroti ketidakmampuan perjanjian penghentian permusuhan untuk melindungi penduduk sipil di wilayah perbatasan selatan Lebanon, di mana serangan udara Israel terus berlanjut di tengah tuduhan balasan terhadap aktivitas Hizbullah.
Thameen Al-Kheetan, juru bicara OHCHR, menyatakan bahwa tim pemantauannya telah mendokumentasikan serangan-serangan udara yang menargetkan desa-desa kecil di Lebanon selatan, seperti Tayr Dibba dan Naqoura, di mana warga sipil menjadi korban utama. “Angka kematian ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan,” ujar Al-Kheetan dalam konferensi pers virtual dari Jenewa. Ia menekankan bahwa sejak gencatan senjata dimulai pada 27 November 2024, lebih dari 500 serangan udara telah tercatat, dengan mayoritas menimbulkan kerusakan pada infrastruktur sipil seperti sekolah, pusat kesehatan, dan lahan pertanian—elemen vital bagi kelangsungan hidup masyarakat yang telah mengungsi selama lebih dari dua tahun konflik.

Pelanggaran ini bukanlah insiden sporadis, melainkan bagian dari eskalasi yang lebih luas. Konflik yang meletus pada Oktober 2023, awalnya sebagai respons terhadap serangan Hizbullah di perbatasan utara Israel, berkembang menjadi invasi darat besar-besaran pada September 2024. Menurut catatan OHCHR, serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 4.000 orang—termasuk kombatan dan sipil—serta melukai hampir 17.000 lainnya. Di antara korban pasca-gencatan senjata, terdapat 71 pria, 21 wanita, dan 16 anak-anak, dengan setidaknya 19 kasus penculikan sipil oleh pasukan Israel yang diduga melanggar konvensi internasional tentang hilang paksa. Laporan juga mencatat kerusakan lingkungan yang parah, termasuk penghancuran zona pertanian yang menyulitkan pemulihan ekonomi di wilayah yang sudah miskin.
Al-Kheetan menyerukan penghentian segera terhadap “dampak mematikan yang terus menerus terhadap warga sipil,” yang menurutnya melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang mewajibkan perlindungan bagi non-kombatan. “Penduduk Lebanon selatan telah hidup dalam ketidakstabilan dan ketakutan yang konstan selama lebih dari dua tahun. Gencatan senjata harus menjadi titik balik menuju perdamaian, bukan alasan untuk impunitas,” tambahnya. Ia juga mendesak kepatuhan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang menuntut penarikan pasukan Israel dari selatan Sungai Litani dan pembubaran infrastruktur militer Hizbullah di wilayah tersebut.
Baca juga : Kolaborasi Kemensos-BPS Capai Tingkat Desa untuk Perkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Dari perspektif akademis, para pakar hukum internasional memandang pelanggaran ini sebagai ujian bagi efektivitas perjanjian multilateral di zona konflik asimetris. Dr. Layla Hassan, dosen hukum humaniter di Universitas Amerika Beirut, menganalisis bahwa ketidakpatuhan Israel—yang dibenarkan sebagai “penegakan ancaman langsung”—menciptakan siklus ketidakpercayaan yang melemahkan fondasi gencatan senjata. “Ini bukan hanya pelanggaran teknis, tapi kegagalan struktural dalam menegakkan akuntabilitas. Tanpa investigasi independen, seperti yang direkomendasikan oleh pakar PBB, risiko eskalasi ulang menjadi sangat tinggi,” kata Hassan dalam wawancara eksklusif. Penelitiannya, yang diterbitkan di Journal of International Humanitarian Law edisi terbaru, menunjukkan bahwa 70% pelanggaran serupa di konflik Timur Tengah sejak 2000 berujung pada perpanjangan permusuhan, dengan korban sipil sebagai yang paling terdampak.
Sementara itu, pemerintah Lebanon, di bawah Presiden Joseph Aoun, telah mengutuk serangan terbaru sebagai “kebijakan sistematis untuk menghambat pemulihan nasional.” Aoun, yang terpilih pada Januari 2025, berupaya mengonsolidasikan kendali senjata di bawah angkatan bersenjata Lebanon, termasuk negosiasi dengan Hizbullah untuk membongkar fasilitas selatan Litani. Namun, tuduhan balik dari Israel—yang mengklaim Hizbullah masih membangun kembali kemampuan militernya—menambah kompleksitas. Analis keamanan regional, seperti yang dikutip dari studi terbaru oleh Arab Center Washington DC, memperingatkan bahwa tanpa mediasi lebih kuat dari mediator seperti Amerika Serikat dan Prancis, gencatan senjata ini berisiko menjadi “jeda sementara” daripada solusi permanen.

Di lapangan, warga seperti Fatima al-Mansour, seorang petani dari desa Ansar yang kehilangan rumahnya dalam serangan Oktober lalu, menggambarkan realitas harian yang mencekam. “Kami mencoba kembali ke tanah kami, tapi setiap hari ada suara ledakan. Anak-anak saya takut tidur, dan panen kami hancur. Kapan perdamaian ini nyata?” tanyanya melalui pesan suara dari pengungsian di Beirut. Kisah-kisah seperti ini, yang didokumentasikan oleh OHCHR, menekankan urgensi pembersihan ranjau tak meledak dan bantuan kemanusiaan untuk memungkinkan kembalinya 90.000 pengungsi Lebanon.
Saat dunia menyaksikan, panggilan untuk akuntabilitas semakin kencang. Pakar PBB telah mengirimkan surat peringatan kepada pemerintah Israel, menuntut kerjasama penuh dalam investigasi, meskipun respons sebelumnya minim. Di tengah tekanan domestik dan internasional, termasuk dari sekutu seperti Amerika Serikat yang kini di bawah administrasi baru, harapan tetap ada pada dialog yang inklusif. Namun, tanpa tindakan konkret, 114 nyawa yang hilang hanyalah awal dari luka yang lebih dalam bagi Lebanon—sebuah negara yang terus bergulat dengan bayang-bayang perang.
Pewarta : Setiawan Wibisono