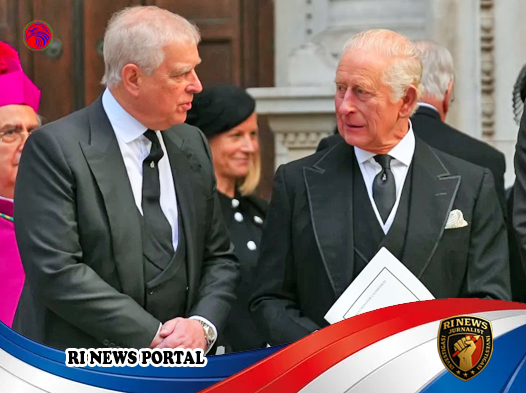RI News Portal. Dhaka – Dalam hitungan hari, Bangladesh akan menggelar pemilu parlemen paling menentukan dalam sejarah modernnya pada 12 Februari 2026. Pemungutan suara ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan penutup babak transisi pasca-revolusi mahasiswa 2024 yang menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa, serta sekaligus referendum konstitusi yang akan membentuk arah politik negara ke depan.
Pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus—penerima Nobel Perdamaian yang kini berusia 85 tahun—telah menjalankan roda negara selama 18 bulan terakhir. Yunus berulang kali menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan adil, sesuatu yang menjadi tuntutan utama rakyat setelah pemilu-pemilu era Hasina dianggap penuh kecurangan dan penindasan oposisi.
Banyak warga melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, dan menghadirkan pemerintahan yang akuntabel. Seorang mahasiswa bernama Arefin Labib menyuarakan keresahan sekaligus harapannya: “Saya tidak ingin lagi ada kekacauan atau situasi seperti perang di Bangladesh. Pemilu yang adil adalah kunci agar negara bisa berjalan lancar dan menuju masa depan yang lebih baik.”

Pemerintahan Yunus memang berhasil menstabilkan ekonomi yang sempat ambruk pasca-gejolak 2024. Namun, kritik tajam muncul terkait kegagalan mengembalikan rasa aman di masyarakat. Kekerasan politik meningkat, serangan terhadap minoritas Hindu berulang, dan perlindungan hak asasi manusia dinilai masih lemah. Seorang pedagang jalanan berusia 62 tahun, Zainul Abedeen, menekankan, “Pemerintah harus mencegah kerusuhan dan pembunuhan. Itu yang paling dibutuhkan rakyat sekarang.”
Warga Dhaka, Rajit Hasan, menambahkan bahwa meski upaya stabilisasi dilakukan, fragmentasi politik yang dalam membuat reformasi mendalam sulit tercapai. “Kami menginginkan demokrasi sejati, supremasi hukum, serta ruang bagi perbedaan pendapat tanpa tekanan,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah representasi perempuan. Bangladesh pernah menjadi sorotan dunia karena dipimpin perdana menteri perempuan selama puluhan tahun. Namun, dalam pemilu kali ini, partai Hasina dilarang berpartisipasi, dan jumlah calon perempuan menurun drastis—padahal perempuan memainkan peran sentral dalam pemberontakan 2024.
Baca juga : Monarki di Persimpangan: Raja Charles Memilih Transparansi di Tengah Badai Epstein yang Kian Menguat
Wasima Binte Hussain, seorang mahasiswi yang ikut dalam revolusi tersebut, mengungkapkan kekecewaannya. “Saya berharap transisi ini membuka lebih banyak ruang bagi pemimpin perempuan dan isu-isu perempuan mendapat prioritas. Sayangnya, itu belum terlihat,” katanya.
Kekhawatiran semakin membesar seiring lonjakan dukungan terhadap Jamaat-e-Islami, kelompok Islamis yang dulu dilarang tapi kini semakin berpengaruh. Pernyataan sebagian pemimpin partai yang mengusulkan pembatasan aktivitas perempuan karena peran reproduksi mereka memicu alarm di kalangan perempuan muda. Sayma Nowshin Suha (22 tahun) menyatakan, “Konservatisme adalah hal paling menakutkan di Bangladesh. Saya bermimpi negara di mana setiap orang bebas menjalani hidup tanpa rasa takut atau batasan.”

Pemilu ini juga diwarnai referendum atas paket reformasi konstitusi yang disebut “Piagam Juli”. Yunus secara aktif mengkampanyekan suara “Ya” agar reformasi tersebut diterima, dengan janji akan segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih. Namun, di tengah ancaman disinformasi asing dan kekerasan sporadis, banyak pihak mempertanyakan apakah proses ini benar-benar akan menjadi tonggak kebangkitan demokrasi atau justru membuka babak baru ketidakstabilan.
Dengan lebih dari 127 juta pemilih terdaftar, Bangladesh berdiri di persimpangan: antara harapan akan tata kelola yang lebih inklusif dan risiko polarisasi yang lebih dalam. Hasil 12 Februari nanti tidak hanya menentukan siapa yang memimpin, tapi juga bagaimana negara ini mendefinisikan dirinya di masa mendatang.
Pewarta : Setiawan Wibisono