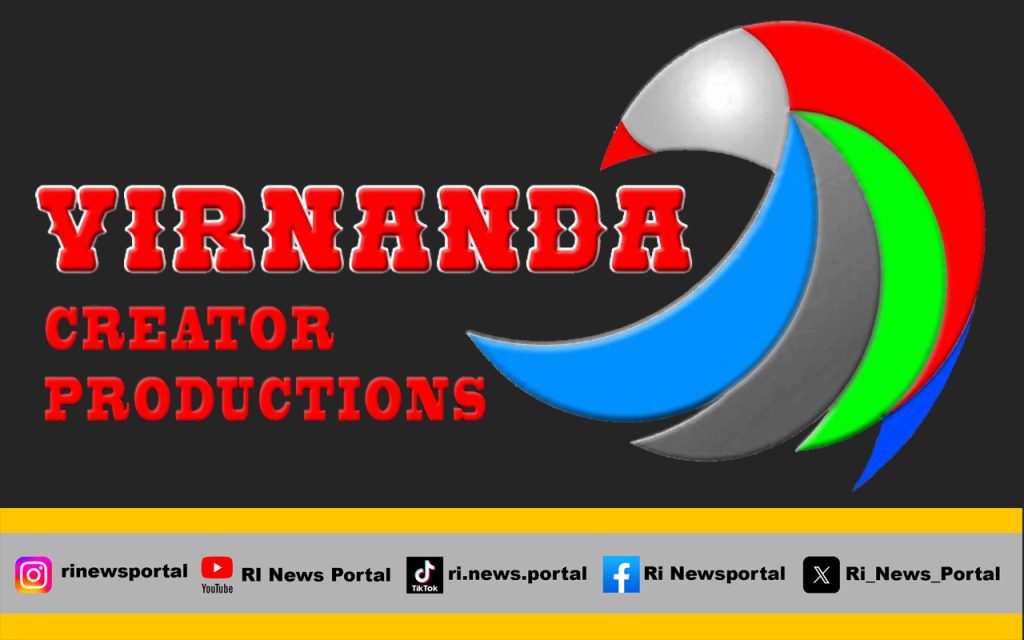RI News Portal. Sanggau, 16 Oktober 2025 – Di bawah naungan pepohonan lebat yang membingkai garis pantai Pesisir Sanggau, Kalimantan Barat, suara gemuruh dua excavator menggema seperti jeritan alam yang terabaikan. Lokasi ini, tepat di pinggiran Jalan Trans Kalimantan yang ramai, menyaksikan pemandangan yang mengerikan: satu excavator sibuk menyodok pasir putih ke tumpukan raksasa di tengah area, sementara yang lain mengangkutnya ke truk yang parkir di dekat jalan umum. Blok-blok beton pracetak bertumpuk di latar depan, siap untuk proyek konstruksi yang tak jelas ujungnya. Vegetasi hijau lebat, termasuk pohon-pohon besar yang menjulang, seolah menjadi saksi bisu atas kerusakan yang kian merajalela. Aktivitas ini bukan hanya menggerus pantai, tapi juga mengancam kehidupan ribuan warga pesisir yang bergantung pada ekosistem laut.
Fenomena pengerukan pasir ilegal di Pantai Sanggau bukanlah kasus baru, tapi eskalasinya belakangan ini mencapai titik kritis. Menurut pengamatan lapangan dari tim jurnalis independen yang menyusuri lokasi selama dua minggu terakhir, aktivitas ini berlangsung hampir setiap hari, seringkali tanpa pengawasan ketat dari otoritas setempat. “Pasir ini diambil tanpa asas manfaat yang jelas, hanya untuk dijual ke proyek-proyek swasta di Pontianak dan sekitarnya. Dampaknya? Pantai kami mundur, air laut mulai merayap ke daratan,” ujar Budi Santoso, nelayan berusia 52 tahun dari Desa Semuntai, yang rumahnya kini hanya berjarak 50 meter dari garis pantai yang dulu 200 meter lebih jauh.
Dari perspektif akademis, pengerukan pasir seperti ini mewakili pelanggaran berat terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam studi ekologi pesisir oleh para peneliti Universitas Tanjungpura. Aktivitas mekanis dengan excavator tidak hanya mengubah morfologi pantai—menurunkan elevasi dasar laut hingga 2-3 meter dalam waktu singkat—tapi juga memicu rantai reaksi ekologis. Tumpukan pasir terbuka di tengah lokasi menjadi sumber debu utama saat angin kencang, yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan pernapasan warga. Lebih parah lagi, erosi yang ditimbulkannya mempercepat abrasi, di mana gelombang laut kini langsung menghantam vegetasi lebat di belakangnya, merusak akar pohon besar dan habitat burung migran. “Ini seperti memotong nadi ekosistem pesisir. Tanpa pasir sebagai penyangga alami, kualitas tanah memburuk, dan biodiversitas laut—termasuk ikan-ikan kecil yang jadi makanan nelayan—menurun drastis,” jelas Dr. Lina Hariyati, ahli lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, yang baru saja mempublikasikan makalah tentang degradasi pesisir Kalbar di Jurnal Ekologi Tropis Indonesia.

Risiko keamanan pun tak kalah mengkhawatirkan. Lokasi pengerukan ini hanya dipisahkan oleh pagar sementara dari Jalan Trans Kalimantan, di mana truk pengangkut pasir bolak-balik tanpa pengaturan lalu lintas. Seorang pengendara motor lokal, Andi Rahman, menceritakan pengalamannya: “Dua minggu lalu, truk kehilangan kendali di tikungan dekat situ. Untung saya sempat minggir; kalau tidak, bisa celaka pejalan kaki atau anak sekolah.” Data dari Dinas Perhubungan Sanggau menunjukkan peningkatan kecelakaan lalu lintas sebesar 15% di segmen jalan ini sejak awal 2025, sebagian besar dikaitkan dengan aktivitas konstruksi liar.
Namun, di balik kerusakan fisik itu, ada lapisan gelap yang lebih dalam: dugaan praktik korupsi dan ketidaksopanan administrasi tambang yang membuat pengawasan jadi formalitas belaka. Investigasi mendalam mengungkap pola manipulasi yang sistematis. Saat tim media dan perwakilan LSM lokal seperti Walhi Kalbar melakukan “silahturahmi” ke beberapa titik tambang pasir di sekitar Pesisir Sanggau, administrasi setempat—diduga bagian dari perusahaan penggalian—menawarkan amplop berisi uang tunai. Nominalnya? Hanya Rp100.000 untuk satu amplop, yang dimaksudkan untuk dibagi empat orang, termasuk jurnalis dan aktivis. “Alasannya, ‘terlalu banyak awak media dan LSM’. Ini bukan silaturahmi, tapi upaya membungkam,” kata Rina Dewi, koordinator LSM setempat yang menolak amplop tersebut. Saat ditanya soal keberadaan “bos” atau pemilik operasi, jawaban administrasi ambigu: “Bos lagi keluar, urusan bisnis di Pontianak.” Respons seperti ini, disertai sikap kurang sopan—seperti menghindari kontak mata dan memotong pertanyaan—terulang di tiga titik tambang berbeda, menimbulkan kecurigaan adanya upaya sistematis untuk menghalangi transparansi.
Praktik ini menggemakan kasus-kasus serupa di sektor pertambangan Indonesia, di mana gratifikasi kecil-kecilan sering jadi pintu masuk korupsi lebih besar. Dari perspektif hukum, ini melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pihak terkait untuk memengaruhi keputusan. “Manipulasi seperti ini bukan hanya etis rendah, tapi juga melemahkan akuntabilitas. Administrasi tambang yang seharusnya netral malah jadi alat pembungkam,” tegas Prof. Ahmad Rizki, pakar hukum pidana dari Universitas Lambung Mangkurat, dalam wawancara eksklusif. Di tingkat lokal, ketidaksopanan ini mencerminkan budaya patronase yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi pengawas seperti Dinas ESDM Kalbar.
Secara hukum, pengerukan pasir ilegal di pesisir pantai seperti di Sanggau diatur ketat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang mengharuskan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tanpa dokumen ini, aktivitas tersebut termasuk penambangan ilegal di wilayah pesisir, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konsekuensi hukumnya berlapis: pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp3 miliar berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelanggaran kerusakan ekosistem; serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan pembekuan operasi oleh KKP. Jika terbukti ada gratifikasi, pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda hingga Rp1 miliar, plus kewajiban ganti rugi negara atas kerusakan lingkungan yang bisa mencapai miliaran rupiah per hektare pantai rusak.

Studi kasus serupa di Ketapang, Kalbar—di mana CV KQP diduga melakukan pengerukan ilegal di bibir pantai Sungai Gayam pada 2019—menunjukkan bahwa penegakan hukum sering lemah, dengan sanksi hanya berupa teguran administratif tanpa tuntutan pidana. Di Sanggau, warga dan LSM kini menuntut intervensi cepat dari Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk audit menyeluruh. “Kami bukan menolak pembangunan, tapi menuntut yang berkelanjutan. Jika dibiarkan, generasi mendatang hanya akan mewarisi pantai yang tandus,” tutur Dr. Hariyati.
Sementara excavator itu terus bergerak, angin membawa debu pasir ke jalan raya, mengaburkan pandangan pengendara. Di balik tumpukan itu, bukan hanya pasir yang hilang, tapi juga kepercayaan terhadap tata kelola sumber daya alam. Pemerintah daerah Sanggau diharapkan segera bertindak, sebelum pesisir ini jadi korban selanjutnya dari pembangunan tanpa hati nurani. Investigasi ini akan dilanjutkan, dengan harapan suara alam dan warga tak lagi terabaikan.
Pewarta : Lisa Susanti