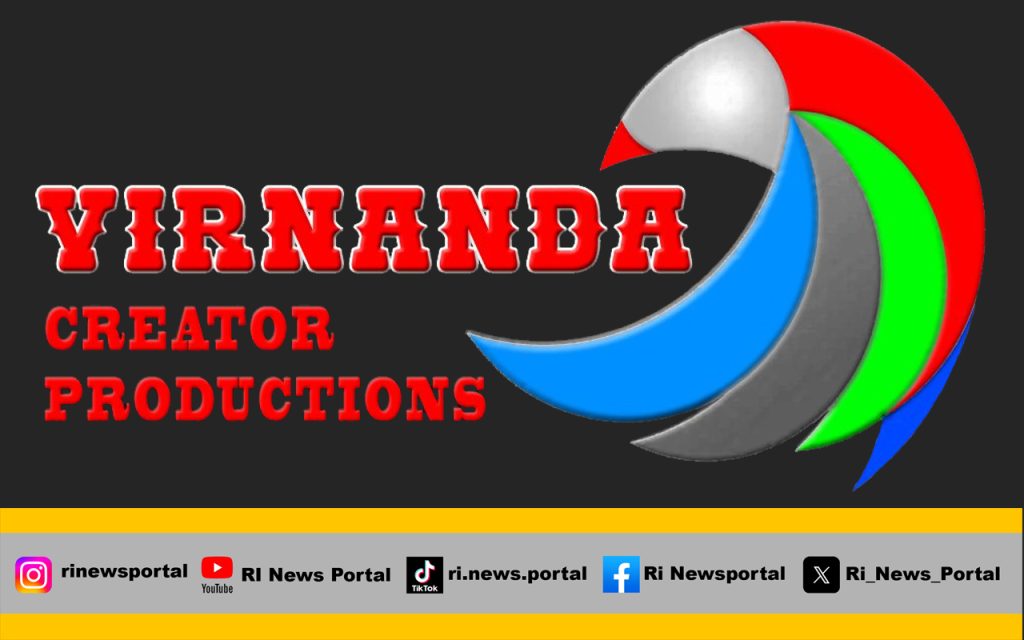RI News Portal. Cairo – Muwasi, Khan Younis, ratusan warga Palestina setiap pagi menyusuri tumpukan sampah dengan tangan telanjang. Mereka mencari botol plastik bekas, kantong kresek, dan potongan styrofoam—bahan apa pun yang bisa dibakar untuk menghasilkan sedikit panas di tengah musim dingin yang basah dan menusuk. Suhu malam kerap turun di bawah 10 derajat Celsius, sementara tenda-tenda pengungsian yang compang-camping hanya dilapisi terpal tipis yang sudah robek-robek.
Pemandangan ini berlangsung hanya beberapa bulan setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober lalu. Namun, bagi keluarga seperti Sanaa Salah—seorang ibu enam anak yang tinggal di tenda bersama suaminya—api dari plastik limbah tetap menjadi satu-satunya sumber kehangatan dan kemampuan memasak. “Kami tahu asapnya beracun, tapi tidak ada pilihan lain,” ujarnya sambil menambahkan potongan plastik ke bara kecil. “Anak-anak tidak bisa tidur karena kedinginan. Secangkir teh hangat saja sudah jadi kemewahan.”
Kontras tajam muncul ketika para pemimpin dunia berkumpul di Davos, Swiss, untuk meresmikan Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump. Dalam forum tersebut, Trump menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan telah mencapai “rekor tertinggi” sejak gencatan senjata, sementara menantu dan utusannya, Jared Kushner, mempresentasikan rencana ambisius “New Gaza”—sebuah visi rekonstruksi yang mencakup pembangunan ribuan unit hunian permanen di Rafah, kawasan industri, pusat data, hingga resor pantai dengan gedung pencakar langit. Peta digital yang ditampilkan membagi Gaza menjadi zona “residensial” dan “pariwisata pantai campuran”, dengan estimasi investasi mencapai miliaran dolar.

Namun di lapangan, realitas jauh berbeda. Meski aliran bantuan makanan dan obat-obatan meningkat, pasokan bahan bakar dan kayu bakar tetap kritis langka. Harga kayu bakar melonjak hingga 7–8 shekel (sekitar Rp 40.000–50.000) per ikat kecil—jumlah yang tidak terjangkau bagi keluarga tanpa penghasilan tetap. Akibatnya, pencarian kayu bakar di daerah terbuka menjadi aktivitas berisiko tinggi. Pekan lalu, dua remaja berusia 13 tahun tewas ditembak pasukan Israel saat mengumpulkan ranting di pinggiran kota.
Serangan sporadis pun belum berhenti sepenuhnya. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza—yang dicatat secara rinci dan dianggap kredibel oleh badan-badan PBB serta pengamat independen—sejak gencatan senjata, lebih dari 470 warga tewas akibat tembakan Israel, termasuk 77 orang di dekat garis demarkasi gencatan senjata. Pekan ini saja, tembakan tank menewaskan empat orang di timur Gaza City, sementara serangan udara menewaskan tiga jurnalis Palestina—salah satunya kontributor tetap agensi berita internasional—saat mereka meliput di dekat kamp pengungsian yang dikelola komite Mesir.
Baca juga : Greenland di Persimpangan Pertahanan Nuklir: Ambisi “Golden Dome” Trump Memantik Ketegangan Arktik
Skeptisisme warga terhadap inisiatif internasional semakin dalam. “Dewan ini melibatkan orang Israel yang selama ini menyebabkan penderitaan kami. Bagaimana kami percaya ini akan mengubah hidup?” tanya Rami Ghalban, seorang pengungsi asal Khan Younis. Bagi Fathi Abu Sultan, harapan pun terasa sia-sia: “Kami tidak punya alternatif lain. Situasi ini sudah terlalu menyedihkan.”
Di sisi lain, ada tanda-tanda perkembangan diplomatik. Perbatasan Rafah dijadwalkan dibuka dua arah mulai minggu depan, memungkinkan akses medis dan kunjungan keluarga ke Mesir. Rusia juga menyatakan kesiapan mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk keperluan kemanusiaan melalui Dewan Perdamaian, dengan syarat AS membuka blokade dana terkait. Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa penyelesaian akhir konflik hanya mungkin melalui pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Sementara itu, di tenda-tenda Gaza, nyala api plastik terus menyala setiap malam—simbol ketahanan sekaligus pengingat bahwa janji pembangunan megah di Davos masih jauh dari kenyataan sehari-hari warga yang berjuang bertahan hidup.
Pewarta : Setiawan Wibisono