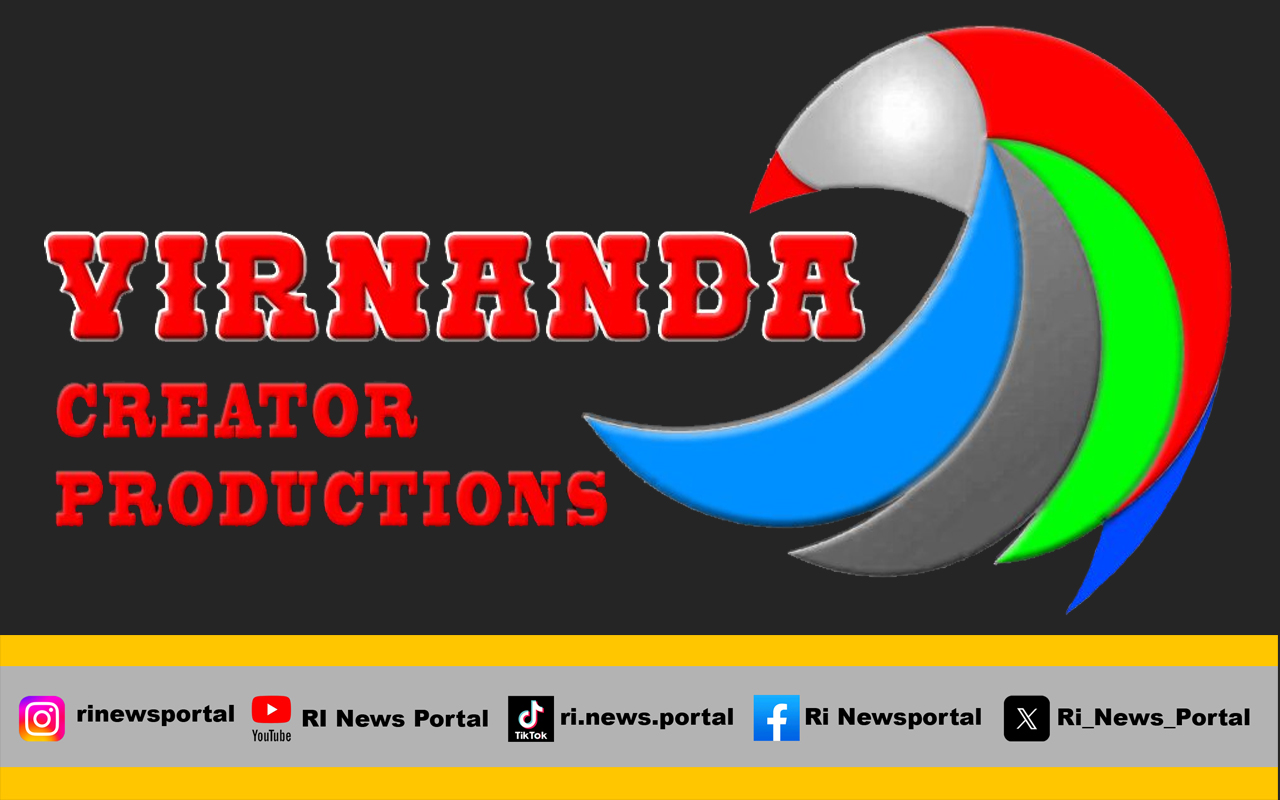RI News Portal. Surakarta, 3 November 2025 – Kabar duka menyelimuti Kota Solo dengan wafatnya Sinuhun Paku Buwono XIII, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kepergian beliau meninggalkan kekosongan takhta yang sarat makna simbolis, di mana putra mahkota, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamangkunegara, disebut-sebut sebagai calon penerus. Meski demikian, pihak keraton belum merilis pengumuman resmi, sehingga proses pewarisan gelar Paku Buwono XIV masih bergantung pada ritual wahyu keprabon yang menjadi inti legitimasi kekuasaan Jawa tradisional.
Kehilangan ini bukan sekadar peristiwa kontemporer, melainkan titik kulminasi dari garis panjang dinasti yang bermula pada abad ke-17, di tengah gejolak Mataram Islam. Gelar Paku Buwono pertama kali disandang Pangeran Puger, putra Amangkurat I dan cucu Sultan Agung, raja agung yang memperluas hegemoni Mataram hingga ke wilayah timur. Munculnya gelar ini tak lepas dari Pemberontakan Trunojoyo, di mana bangsawan Madura itu, dibantu pasukan Makassar dan kelompok oposisi, merebut Kraton Pleret serta menjarah harta kerajaan. Ini menjadi kali pertama Mataram runtuh di tangan pemberontak, meski VOC akhirnya turut campur untuk memulihkan stabilitas—dengan imbalan pengaruh yang semakin dalam.
Dalam kekacauan pasca-pemberontakan, Pangeran Puger menggulingkan keponakannya, Amangkurat III, dan naik takhta sebagai Paku Buwono I. Upayanya memulihkan kerajaan berlangsung selama 15 tahun, hingga digantikan putranya, Amangkurat IV. Gelar Paku Buwono baru kembali muncul pada masa cucunya, Paku Buwono II, yang justru menjadi katalisator perpecahan besar di Tanah Jawa.

Paku Buwono II dikenang sebagai figur kontroversial: berhati lembut namun rentan manipulasi, khususnya oleh VOC. Awal pemerintahannya menunjukkan dukungan terhadap aliansi Jawa-Tionghoa melawan Belanda, tetapi sikapnya berbalik ketika tekanan militer meningkat. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam analisisnya menyoroti bagaimana perubahan ini memicu kekecewaan massal di kalangan bangsawan dan rakyat, yang akhirnya mengangkat Raden Mas Garendi—seorang anak berusia 12 tahun—sebagai raja saingan. Kartasura pun chaos; dinding kraton roboh, dan Paku Buwono II terpaksa mengungsi ke Ponorogo bersama perwira VOC, Van Hohendorff.
Dalam posisi terdesak, sang raja memohon intervensi VOC untuk merebut kembali kekuasaan, dengan janji menyerahkan kontrol atas wilayah pesisir dan pejabat tinggi. Kesepakatan ini, seperti digambarkan sejarawan De Graaf, menjadi “angin segar” bagi ambisi kolonial Batavia, yang secara efektif mulai menggerogoti kedaulatan Mataram. Meski VOC berhasil mengembalikan Paku Buwono II, ibu kota Kartasura telah hancur lebur. Ia lantas memindahkan pusat pemerintahan sekitar 12 kilometer ke timur Sungai Sala, mendirikan Surakarta—kota yang kini menjadi saksi bisu warisan dinasti ini.
Baca juga : Klarifikasi Pemkot Semarang: Aksi Damai di RSUD KRMT Wongsonegoro Murni Sengketa Antar-Rekanan Swasta
Pemindahan ibu kota tak menghentikan resistensi. Pangeran Mangkubumi (kelak Sultan Hamengku Buwono I) dan Raden Mas Said (kelak Mangkunegara I) terus melancarkan perlawanan terhadap VOC serta Kasunanan. Konflik memuncak saat Paku Buwono II mengingkari janji tanah kepada Mangkubumi pasca-kemenangan di Sukowati, memicu pemberontakan skala besar dengan ribuan prajurit.
Di puncak perang ini, Paku Buwono II wafat, meninggalkan takhta kepada Paku Buwono III yang masih muda. Negosiasi paksa dengan VOC dan kubu Mangkubumi berujung pada Perjanjian Giyanti 1755, yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Paku Buwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sultan Hamengku Buwono I. Dua tahun kemudian, Raden Mas Said berdamai dan mendapat Kadipaten Mangkunegaran. Era Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles (1811–1816) menambah fragmentasi dengan memisahkan Kadipaten Pakualaman dari Yogyakarta, dipimpin Paku Alam I.
Sejak itu, Jawa diperintah oleh empat dinasti keturunan Mataram: Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Mereka bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga simbol ketahanan budaya di tengah arus modernisasi. Transisi takhta saat ini, dengan segala ketidakpastiannya, mengingatkan kita pada fragilitas kekuasaan yang telah berulang kali diuji sejarah—dari kejayaan Sultan Agung hingga kompromi pahit dengan kekuatan asing.
Dalam konteks akademis, peristiwa ini membuka ruang diskusi tentang kontinuitas institusi monarki tradisional di Indonesia pasca-kemerdekaan. Siapa pun yang akhirnya menerima wahyu keprabon sebagai Paku Buwono XIV, akan membawa beban warisan yang tak hanya simbolis, tapi juga tantangan adaptasi di era demokrasi kontemporer.
Pewarta :Nandar Suyadi