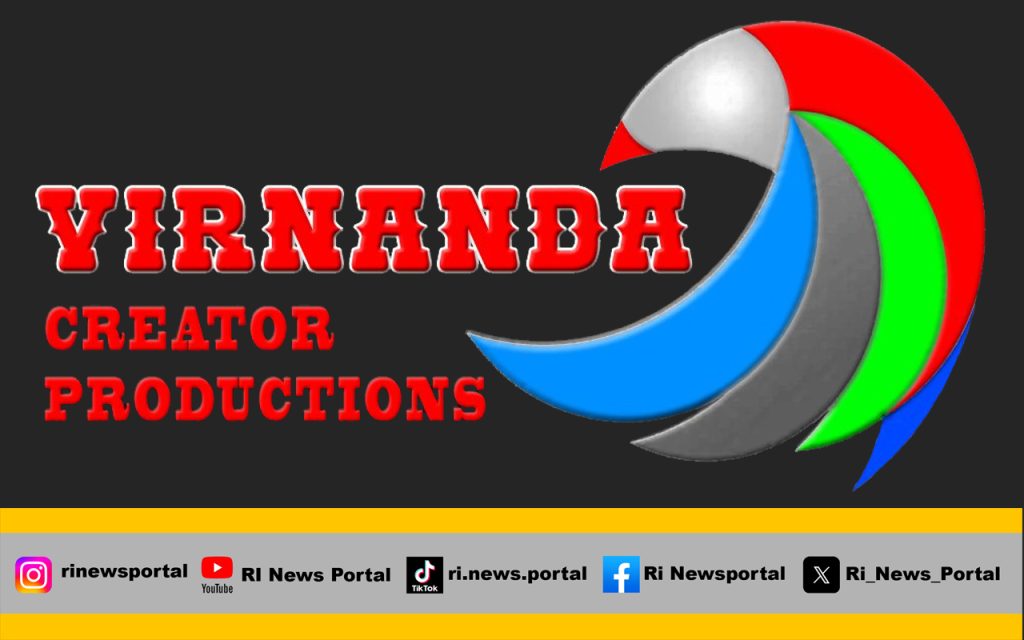RI News Portal. Subulussalam, 1 November 2025 – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan perkebunan sawit yang menjanjikan kemakmuran, sebuah pola gelap mulai terkuak di Kota Subulussalam, Aceh. Di balik kemasan mulia Corporate Social Responsibility (CSR), dua perusahaan pengolahan sawit—PT Mandiri Sawit Bersama II (PT MSB II) dan PT Sawit Panen Terus (PT SPT)—diduga menggunakan bantuan infrastruktur sebagai alat tukar untuk melicinkan operasi tanpa izin lengkap. Isu ini tak hanya menggugat integritas perizinan, tapi juga menimbulkan kecemburuan sosial yang dalam, di mana pelaku usaha lokal merasa terpinggirkan sementara lingkungan alam setempat terancam rusak permanen.
Adi Subandi, Ketua LSM Aliansi Peduli Indonesia (API) cabang DPD Kota Subulussalam, tak segan menyebut praktik ini sebagai “dalih berbalut gratifikasi”. “Satu sisi, perusahaan ini beroperasi tanpa izin operasional dasar seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin lingkungan lainnya. Di sisi lain, pemerintah kota menerima bantuan CSR mereka, seperti penyerahan satu unit bus sekolah dari PT MSB II. Ini bukan kebaikan semata, tapi dugaan barter yang melanggar etika tata kelola,” tegas Subandi saat ditemui di pinggir Sungai Sultan Daulat, belum lama ini. Sebagai relawan senior yang dikenal vokal dalam isu lingkungan Aceh, Subandi menyoroti bagaimana kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam cenderung mengistimewakan investor luar daerah, sementara pengusaha pribumi lokal justru dibebani birokrasi berlapis.
Fenomena ini bukan sekadar tuduhan kosong. Berdasarkan temuan LSM API dan kelompok advokasi lingkungan, PT MSB II dan PT SPT, keduanya berbasis di Kecamatan Sultan Daulat, telah beroperasi sejak awal 2024 tanpa dokumen lengkap. PT MSB II, misalnya, diketahui membuang limbah ke Sungai Rikit dan Sungai Batu-Batu, menyebabkan matinya ikan massal dan bau menyengat yang meresahkan warga Dusun Rikit. Sementara PT SPT diduga merambah hutan lindung di sekitar Desa Singgersing tanpa AMDAL, membuat Sungai Singgersing keruh dan dangkal—ancaman langsung bagi ekosistem Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang dilindungi secara nasional.

Lidin Padang SH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Subulussalam, mengakui ketidaksempurnaan ini dalam pernyataan resminya baru-baru ini. “Kedua perusahaan memang masih dalam proses pengurusan izin, termasuk AMDAL dan IMB. Kami beri ruang untuk melengkapi, tapi operasional tak boleh melewati batas,” ujarnya di ruang kerjanya. Namun, pengakuan ini justru memicu kritik: mengapa operasi tetap jalan, sementara rekomendasi Gubernur Aceh untuk menutup perusahaan bermasalah masih menggantung di meja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)?
Yang lebih menyakitkan bagi warga lokal adalah diskriminasi dalam penerbitan Surat Penunjukan (SP) usaha. “SP untuk perusahaan luar seperti PT MSB II dan PT SPT lolos dengan cepat, bahkan dengan dugaan lobi politik. Sementara pengusaha sawit pribumi dari kampung kami ditolak mentah-mentah, dengan alasan dokumen kurang,” keluh seorang petani kelapa sawit asal Desa Namo Buaya, yang enggan disebut namanya karena takut represali. Subandi menambahkan, “Ini menciptakan kecemburuan sosial yang akut. Pengusaha lokal, yang mayoritas pribumi Aceh, merasa dipersulit birokrasi, sementara perusahaan nasional datang dengan ‘kado’ CSR dan langsung dapat lampu hijau. Akibatnya, ekonomi lokal mandek, sementara sawit mereka merajalela.”
Baca juga : Indonesia di Persimpangan Diplomasi: Peluang Normalisasi dengan Israel di Bawah Bayang Gencatan Senjata Gaza
Data internal API menunjukkan, sejak 2023, setidaknya lima usaha sawit lokal gagal dapat SP karena “ketidaksesuaian administratif”, sementara dua perusahaan luar daerah—termasuk PT MSB II—beroperasi meski izinnya “proses”. Ini bukan hanya soal ekonomi; ini soal keadilan sosial di tanah Aceh yang kaya sumber daya alam. “Kami kecewa berat. SP perusahaan luar diloloskan, lokal ditolak. Ini menguatkan dugaan permainan izin sawit,” tegas Subandi, yang juga dikenal sebagai relawan Prabowo di Aceh.
Puncak kontroversi adalah pemberian satu unit bus sekolah dari PT MSB II kepada Pemko Subulussalam, yang diklaim sebagai bagian CSR. Publik langsung curiga: izin belum lengkap, operasi tetap jalan, lalu tiba-tiba ada ‘hadiah’ berharga. “Izin belum tuntas, tapi bus sekolah sudah diserahkan. Aneh kalau bukan gratifikasi. Lalu apa namanya?” tanya seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sultan Daulat, yang mewakili suara ratusan warga terdampak pencemaran.
LSM API tak ragu mengklasifikasikan ini sebagai pelanggaran Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). “Setiap pemberian dari pihak berbisnis kepada pejabat publik, apalagi yang punya kepentingan izin, bisa dikategorikan gratifikasi atau suap. CSR jangan jadi alat barter untuk melanggengkan pelanggaran,” desak Subandi. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Subulussalam dan Tim Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Polres setempat untuk memeriksa dugaan lobi politik di balik rekomendasi SP untuk PT MSB II. “Jangan sampai bantuan CSR jadi tameng untuk langgar aturan. Aparat hukum harus turun tangan, audit lobi-lobi itu.”
Lebih dari gratifikasi, isu ini menggugat kelestarian alam Subulussalam—kota yang bangga dengan julukan “1001 Air Terjun”. Pencemaran Sungai Rikit oleh PT MSB II telah mematikan sumber penghidupan nelayan, dengan limbah B3 yang diduga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Sementara PT SPT, dengan land clearing ilegal sejak Januari 2024, merusak 14 hektare hutan lindung, membuat Sungai Singgersing tak lagi layak irigasi. “Ekosistem KEL terancam. Ikan mati, air keruh, tanaman sawit merajalela. Ini bukan kemajuan, tapi kehancuran berkelanjutan,” papar Subandi.
Mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Syiah Kuala (USK) bahkan mendukung ultimatum Pemko untuk tutup sementara kedua perusahaan, menekankan kewenangan Walikota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, hingga kini, operasi tetap berlanjut—memicu aksi damai dari aliansi buruh dan tani yang khawatir hilangnya lapangan kerja.
Subandi menutup wawancaranya dengan nada harap: “Persoalan ini perlu dikaji ulang. Surat Gubernur Aceh masih bergulir di meja KLHK—semoga segera ada penutupan untuk perusahaan bermasalah. Kami minta transparansi penuh: audit CSR, cabut SP ilegal, dan lindungi usaha lokal.” Bagi Subulussalam, ini bukan akhir cerita, tapi panggilan untuk reformasi tata kelola yang adil, di mana CSR benar-benar untuk rakyat, bukan alat permainan kekuasaan.
Sementara sungai-sungai setempat terus mengalir keruh, pertanyaan menggantung: akankah keadilan lingkungan dan sosial jadi prioritas, atau sawit tetap jadi raja tanpa mahkota?
Pewarta : Jaulin Saran