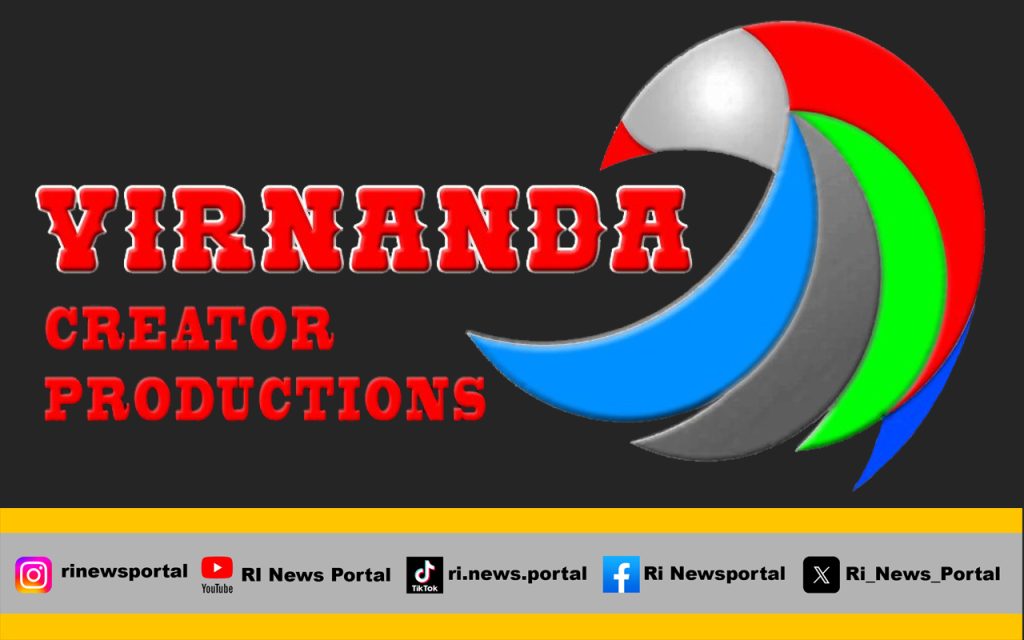RI News Portal. Jakarta, 2 Oktober 2025 – Dalam persidangan yang semakin memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, aktris dan selebriti Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan dengan interupsinya yang tegas terhadap ilustrasi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Insiden ini terjadi pada sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman melalui media sosial serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang melibatkan Nikita dan dokter kecantikan Reza Gladys. Berbeda dari liputan media konvensional yang sering kali terpaku pada drama emosional, analisis ini menyoroti implikasi lebih luas terhadap interpretasi hukum digital dan ketidakadilan struktural dalam representasi status sosial di era media sosial.
Persidangan hari itu difokuskan pada pemeriksaan saksi ahli bidang Informasi dan Teknologi (ITE), Andy Widianto, yang sebelumnya membahas perbedaan status sosial dalam konteks logika hukum. Saat JPU berupaya mengilustrasikan konsep tersebut, suasana ruang sidang tiba-tiba tegang. Dengan nada yang penuh keyakinan, salah satu jaksa menyampaikan: “Saudara ahli, terkait dengan yang tadi pasal 29 bahwa ada perbedaan status dengan kita menggunakan logika hukum, ya. Saya tertarik dengan logika hukum, ya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang public figure, terus kemudian dia mempunyai banyak followers, mau ngomong benar kek, mau ngomong salah kek, semua orang akan percaya.”
Ilustrasi itu dilanjutkan dengan penekanan pada pengaruh komunitas digital: “Jadi sudah punya suatu komunitas tersendiri yang banyak mendengarkan, orang banyak mendengarkan, dan oh pasti benar tuh kalau dia yang ngomong. Mau benar, mau salah, pasti benar, gitu ya.” Jaksa kemudian menghubungkannya dengan dinamika hierarki: “Dikaitkan dengan seseorang yang profesinya tidak ada, apa tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, yang lebih di bawahnya. Kalau dari logika hukumnya apakah hal itu masuk? Dengan posisi yang di atas dan di bawah? Tadi kan ada pimpinan dan bawahan.”

Ucapan itu seolah menyiratkan ketidakseimbangan kekuasaan antara Nikita sebagai figur publik berpengaruh dan Reza Gladys, yang digambarkan dalam konteks posisi “bawah”. Respons Nikita instan dan vokal, memotong alur pertanyaan dengan keberatan formal: “Keberatan yang mulia. Keberatan karena dia memberikan contohnya fitnah yang mulia followers nya saya sama Reza lebih banyakkan Reza. Reza Gladys juga public figure.” Ia menegaskan, “Kalau kasih contoh jangan fitnah setara kok, itu fitnah.” Interupsi ini bukan sekadar reaksi pribadi, melainkan pembelaan terhadap narasi yang berpotensi mendiskreditkan integritas korban atau terdakwa berdasarkan metrik digital yang subyektif.
Meskipun demikian, majelis hakim meminta JPU untuk melanjutkan pertanyaan, menjaga kelancaran prosedur. Namun, momen ini mengungkap lapisan yang lebih dalam dalam kasus hukum yang melibatkan elemen digital. Dari perspektif akademis, ilustrasi JPU mencerminkan perdebatan klasik dalam studi hukum media: bagaimana pengaruh sosial media diukur dan diterapkan dalam kerangka pidana? Menurut teori “network power” yang dikembangkan oleh ahli sosiologi digital seperti Manuel Castells, jumlah followers bukanlah indikator mutlak kebenaran atau otoritas, melainkan konstruksi sosial yang rentan terhadap bias algoritma. Di sini, perbandingan status sosial antara Nikita—dengan jutaan pengikut di platform seperti Instagram dan X—dan Reza Gladys, yang juga aktif sebagai influencer kecantikan, menimbulkan pertanyaan etis: Apakah hukum boleh menggeneralisasi “kekuasaan atas” berdasarkan metrik vanity seperti itu, tanpa bukti empiris dampak nyata terhadap korban?
Baca juga : Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga Nasional
Kasus ini berakar pada tuduhan bahwa Nikita dan asistennya, Mail Syahputra, melakukan pengancaman elektronik untuk memeras Rp4 miliar dari Reza, sebagai imbalan atas diamnya kritik terhadap produk skincare Gladys yang diduga bermasalah. Sejak laporan polisi pada Desember 2024, persidangan telah diwarnai kontroversi, termasuk klaim Nikita soal kriminalisasi dan saksi-saksi yang mengungkap ketidakpatuhan regulasi produk Reza. Namun, interupsi hari ini menyoroti risiko fitnah implisit dalam proses hukum: ketika ilustrasi jaksa menyiratkan superioritas digital terdakwa, hal itu bisa memperkuat stereotip gender dan kelas dalam litigasi selebriti, di mana perempuan publik sering kali dihakimi bukan atas fakta, melainkan persona online mereka.
Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menggemakan isu-isu dalam jurnal hukum kontemporer, seperti yang dibahas dalam Journal of Digital Law edisi terbaru, di mana peneliti menekankan perlunya pedoman forensik digital yang netral gender untuk menghindari bias hierarkis. Nikita, yang dikenal vokal dalam advokasi hak perempuan, tampaknya menggunakan momen ini untuk menantang narasi tersebut, menuntut kesetaraan dalam representasi. “Fitnah seperti itu merusak proses adil,” katanya pasca-sidang, menurut sumber dekat, meskipun ia menolak wawancara mendalam.
Sidang lanjutan dijadwalkan dua minggu lagi, dengan kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi ahli. Sementara media massa cenderung mengeksploitasi elemen sensasional—seperti teriakan atau air mata—pendekatan ini mengajak kita merefleksikan: Di tengah ledakan konten digital, bagaimana sistem peradilan kita memastikan bahwa logika hukum tidak terjebak dalam ilusi pengaruh virtual? Jawaban atasnya mungkin menentukan arah keadilan di era pasca-kebenaran, di mana satu tweet bisa mengubah nasib seseorang, tapi juga membuka pintu bagi reformasi yang lebih inklusif.
Pewarta : Vie