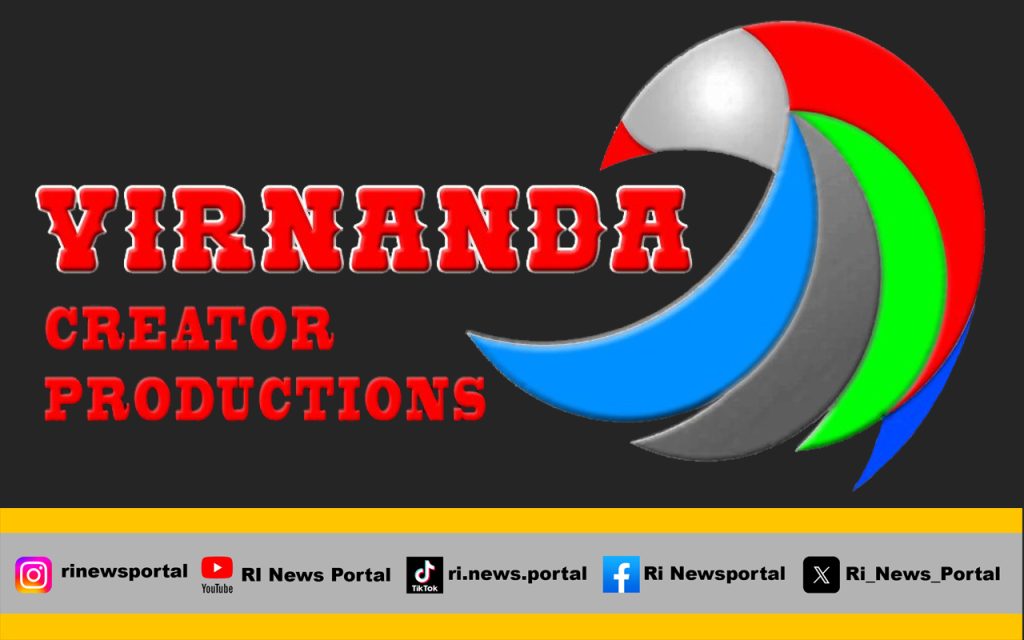RI News Portal. Jakarta, 30 September 2025 – Hari ini menandai lima tahun sejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, selama kegiatan tersebut tidak menciptakan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Pernyataan pada 29 September 2020 itu bukan hanya respons terhadap rencana nonton bareng (nobar) oleh kelompok tertentu, melainkan cerminan evolusi dalam penanganan memori kolektif bangsa, di mana sejarah sensitif seperti Gerakan 30 September (G30S) mulai didekati dengan keseimbangan antara kebebasan ekspresi dan kehati-hatian sosial.

Film Pengkhianatan G30S/PKI, yang dirilis pada 1984 di bawah rezim Orde Baru, awalnya berfungsi sebagai alat propaganda untuk mengukuhkan narasi resmi tentang peristiwa G30S 1965. Disutradarai oleh Arifin C. Noer dan diproduksi oleh pemerintah, film ini menggambarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat, lengkap dengan adegan dramatis yang sering dikritik karena berlebihan dan fiktif. Selama era Soeharto, film berdurasi sekitar empat jam ini wajib ditayangkan setiap 30 September di TVRI dan stasiun swasta, membentuk generasi dengan pandangan hitam-putih terhadap sejarah, di mana PKI digambarkan sebagai musuh utama negara. Tujuannya jelas: memperkuat legitimasi Orde Baru sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme, sekaligus membenarkan pembantaian massal pasca-1965 yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang.

Namun, narasi ini mulai retak pasca-reformasi. Pada 1998, Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto setelah krisis ekonomi dan demonstrasi mahasiswa, memutuskan untuk melarang penayangan film tersebut di televisi. Keputusan ini didasari keyakinan bahwa bangsa harus bergerak maju, bukan terjebak dalam “kubangan masa lalu”. Dalam wawancara yang dikutip dari berbagai sumber, Habibie menyatakan, “Saya tidak mau mengeluarkannya bila terus terang. Saya tidak benarkan meluangkan waktu yang saya miliki hanya 24 jam sehari untuk menggali masa lampau. Saya tidak mau. And itu kenapa, salah. Banyak bangsa-bangsa gara-gara itu tak maju-maju.” Ia juga menekankan rekonsiliasi: “Udah deh semua pahlawan… Saya harus membereskan banyak yang anti, yang anti juga saya rangkul peluk, karena mereka juga saudara saya.” Larangan ini menjadi simbol transisi demokrasi, di mana pemerintah mulai mengakui bahwa propaganda Orde Baru telah membelenggu diskusi terbuka tentang sejarah.
Baca juga : Debut yang Menantang El Putra Sarira dan Leya Princy di Film Rangga & Cinta
Fast-forward ke era Joko Widodo, narasi lama tentang “kebangkitan PKI” muncul kembali, terutama di kalangan kelompok konservatif dan mantan militer seperti eks-Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pada 2020, rencana nobar film G30S/PKI oleh berbagai organisasi, termasuk kelompok militer, memicu kontroversi. Di tengah kekhawatiran pandemi, Mahfud MD merespons dengan tegas namun fleksibel: “Pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tetapi juga tidak mewajibkan. Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apa pun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang.” Pernyataan ini menekankan prinsip sukarela—bukan paksaan seperti di era Orde Baru—dan mengintegrasikan konteks kesehatan publik, mencerminkan pendekatan pemerintahan yang lebih pragmatis.
Dari perspektif akademis, peristiwa ini mengilustrasikan dinamika memori kolektif di Indonesia, di mana sejarah bukan hanya fakta, melainkan arena perebutan kekuasaan. Seperti dibahas dalam studi tentang politik memori, film G30S/PKI telah bertransisi dari alat indoktrinasi menjadi objek diskusi kritis, terutama di media baru seperti platform digital. Di era pasca-reformasi, generasi muda semakin mempertanyakan narasi resmi melalui film dokumenter alternatif seperti The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer, yang mengeksplorasi sisi gelap pembantaian 1965. Ini menunjukkan bahwa larangan atau izin pemutaran bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya rekonsiliasi nasional, di mana bangsa belajar dari trauma masa lalu tanpa mengulang polarisasi.
Lima tahun kemudian, refleksi ini relevan di tengah polarisasi politik kontemporer. Apakah film seperti ini masih diperlukan untuk pendidikan sejarah, atau justru menghambat dialog inklusif? Pernyataan Mahfud MD pada 2020 menawarkan model: kebebasan dengan tanggung jawab, memastikan bahwa memori bangsa tidak lagi menjadi alat manipulasi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih adil.
Pewarta : Yudha Purnama