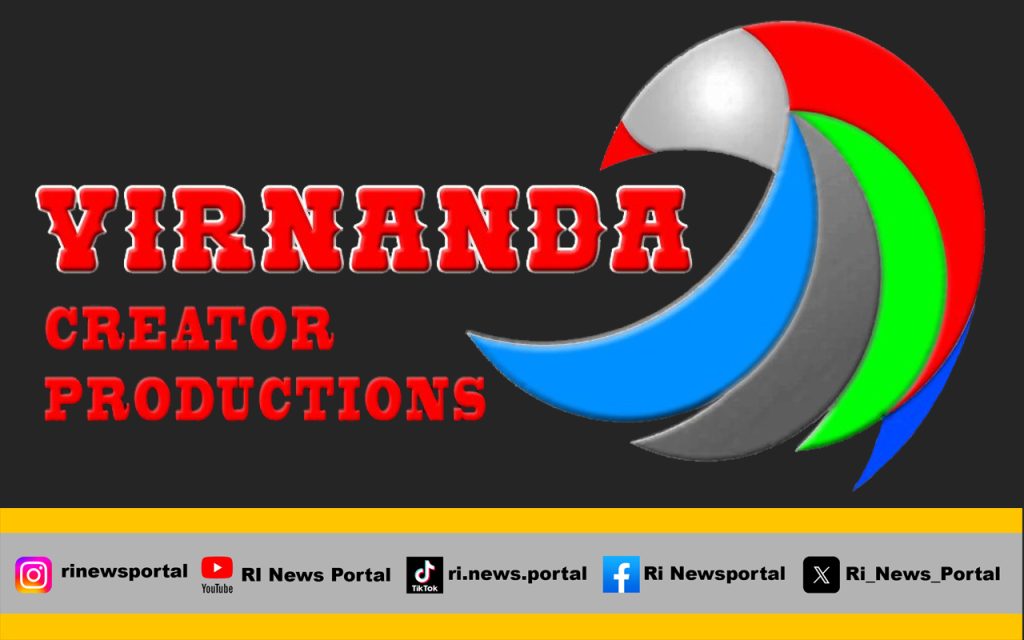RI News Portal. Jepara, 25 September 2025 – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Jepara, kehadiran Bupati Edy Supriyanta pada 24 September kemarin menjadi sorotan utama. Janji yang pernah diucapkan dalam pertemuan sebelumnya akhirnya terbukti, membawa hembusan angin segar bagi warga yang telah lama menanti kepastian dari pemimpin daerah mereka. Namun, momen yang seharusnya menjadi panggung sinergi antara pemerintah kabupaten, aparatur desa, dan masyarakat justru meninggalkan jejak tanda tanya besar akibat absennya perangkat desa di lokasi acara.
Kedatangan bupati ini, yang disambut antusias oleh ratusan warga, seolah membuktikan bahwa komitmen terhadap keresahan rakyat masih menjadi prioritas. Dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal, kehadiran seorang bupati secara langsung ke tengah masyarakat bukan hanya gestur simbolis, melainkan manifestasi dari prinsip akuntabilitas publik yang sering dibahas dalam studi administrasi publik. Seperti yang dikemukakan oleh ahli tata pemerintahan dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ahmad Rizali, dalam karyanya tentang desentralisasi di Indonesia, “Kepemimpinan daerah yang efektif harus dibangun dari bawah, dengan melibatkan semua lapisan birokrasi untuk menghindari kesenjangan antara janji dan realitas.”

Namun, euforia itu cepat pudar ketika perangkat desa—yang seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi terdepan—tak kunjung muncul. Ketidakhadiran ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan memicu kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Seorang tokoh warga, yang enggan disebut namanya, menyatakan kekecewaannya secara lugas: “Kami sangat menghargai Bupati yang memenuhi janjinya, tapi perangkat desa yang hidup sehari-hari bersama kami justru hilang. Ke mana mereka? Ini seperti mengabaikan tanggung jawab moral mereka.”
Dari perspektif akademis, absennya perangkat desa ini dapat dianalisis melalui lensa teori agency dalam ilmu politik, di mana agen (dalam hal ini aparatur desa) sering kali gagal menyelaraskan tindakan mereka dengan prinsipal (pemerintah kabupaten dan masyarakat). Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal, sebagaimana dibahas dalam jurnal Public Administration Review edisi terkini, yang menyoroti bagaimana ketidakselarasan birokrasi tingkat bawah dapat merusak kepercayaan publik. Warga lain yang hadir menambahkan, “Jika Bupati saja bisa menyempatkan waktu, mengapa perangkat desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah justru absen? Ada apa di balik ini?”
Baca juga : Jejak Gelap Mafia Solar di Minahasa: Kolaborasi Ilegal yang Menggerus Subsidi Energi dan Kepercayaan Publik
Situasi ini tak hanya meninggalkan kesan jarak antara kabupaten dan desa, tapi juga memperkuat persepsi ketidakseriusan aparatur desa dalam menjalankan fungsi mereka. Seharusnya, kehadiran bupati menjadi katalisator untuk memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, sebagaimana dianjurkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan peran desa sebagai unit otonom yang harus aktif dalam forum publik. Alih-alih, absennya mereka justru mencoreng momentum kebersamaan, mengubah apa yang bisa menjadi contoh baik menjadi pelajaran pahit tentang inkonsistensi birokrasi.
Di satu sisi, apresiasi masyarakat terhadap bupati tetap tinggi sebagai bukti komitmen nyata. Namun, rasa kecewa terhadap perangkat desa tak terbendung, memunculkan tuntutan transparansi. Kini, sorotan beralih ke aparatur desa untuk memberikan penjelasan yang jujur. Tanpa itu, erosi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa bisa semakin dalam, sebagaimana terlihat dalam studi kasus serupa di daerah lain di Jawa Tengah.
Masyarakat Jepara berharap kejadian ini menjadi titik balik. Perangkat desa dituntut untuk lebih peka, tidak hanya bertugas di balik meja, tapi benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segala urusan pribadi atau kelompok. Dalam era desentralisasi ini, sinergi antarlapisan pemerintahan bukan pilihan, melainkan keharusan untuk membangun tata kelola yang inklusif dan responsif.
Pewarta : Miftahkul Ma’na