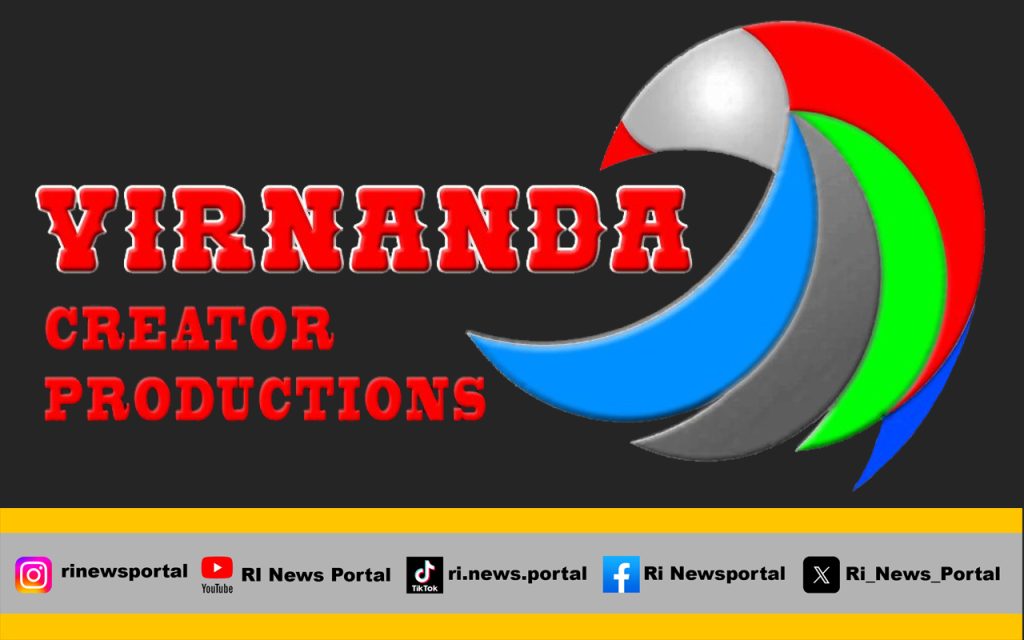RI News Portal. Tapanuli Selatan 24 September 2025 – Dunia peradilan dan politik Indonesia kembali bergolak di tengah dugaan skandal korupsi berskala besar yang menyasar penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus yang terungkap melalui laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan warga ini kini menjadi medan perang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan implikasi yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas keuangan nasional.
Penyelidikan intensif KPK sejak awal September telah membuahkan hasil konkret: penetapan dua anggota Komisi XI DPR RI, Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), sebagai tersangka utama. Langkah ini tidak hanya menandai eskalasi kasus, tetapi juga membuka tabir jaringan yang lebih luas, melibatkan puluhan pemilik tanah sebagai saksi potensial. Dalam konteks akademis, kasus ini menggambarkan dinamika korupsi struktural di mana dana CSR—yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan—berubah menjadi alat eksploitasi elit, sebagaimana dianalisis dalam kerangka teori korupsi kolektif oleh para ahli tata kelola publik seperti Robert Klitgaard.
Intensitas pemeriksaan KPK mencapai puncaknya pada pertengahan September, dengan total 23 pemilik tanah yang dipanggil sebagai saksi. Pada Rabu, 17 September, delapan individu—SU, SR, RP, AS, HS, HSO, FH, dan AK—dihadapkan dengan pertanyaan tajam mengenai aliran dana CSR yang diduga disalahgunakan untuk akuisisi aset pribadi. Tak lama berselang, Kamis 18 September menyusul delapan nama lagi: SA, HL, RA, EF, ESM, DK, AP, dan OM. Klimaks terjadi Jumat 19 September, ketika tujuh pemilik tanah—OL, PP, TS, DAS, MBS, IS, dan SZ—dipersiksa di Gedung Merah Putih KPK.

“Pemeriksaan ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama OL, PP, TS, DAS, MBS, IS, dan SZ, selaku pemilik tanah,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam pernyataan resminya. Dari perspektif jurnalisme investigatif, pola pemanggilan massal ini mencerminkan strategi KPK untuk memetakan rantai pasok korupsi, di mana saksi-saksi ini kemungkinan terhubung melalui transaksi properti yang didanai oleh alokasi CSR senilai miliaran rupiah. Namun, tantangan etis muncul: bagaimana menjaga kerahasiaan saksi di tengah tekanan politik yang kian menumpuk?
Kasus ini tak hanya menjadi urusan lembaga penegak hukum, tetapi juga panggung bagi masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) melangkah maju dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan KPK pada Senin, 22 September. Ketua AMPUH, Muhammad Hadi Susandra Lubis, secara vokal mendesak perluasan penyidikan yang melampaui dua tersangka awal, menyasar figur-figur lain yang disinyalir terlibat, termasuk Gus Irawan Pasaribu—Bupati Tapanuli Selatan sekaligus kader Partai Gerindra.
“Saya mendesak kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Gus Irawan Pasaribu, yang juga kader Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar segera diproses serius. KPK sudah menetapkan dua tersangka terkait persoalan CSR BI-OJK, dan ini harus menjadi atensi dalam rangka penegakan supremasi hukum,” tegas Hadi. Pernyataan ini berakar pada prinsip hukum konstitusional Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di depan hukum, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menekankan transparansi tanpa pandang bulu.
Desakan AMPUH ini bukan sekadar seruan retoris; ia merepresentasikan gelombang aktivisme sipil yang semakin vokal di era digital, di mana platform media sosial mempercepat penyebaran informasi dan tekanan publik. Secara akademis, hal ini selaras dengan konsep “social accountability” yang dikembangkan oleh Jonathan Fox, di mana masyarakat berperan sebagai pengawas independen terhadap institusi negara.
Di sisi lain, Gus Irawan Pasaribu menjawab tudingan dengan nada percaya diri yang kontras. Dalam wawancara eksklusif, ia menepis kekhawatiran atas penyelidikan KPK, menekankan bahwa kerjasamanya dengan BI lebih berorientasi pada inisiatif digitalisasi layanan publik daripada pengelolaan dana CSR. “Belakangan ini saya lebih fokus pada program digitalisasi dengan BI. Jadi kalau ada pihak yang menyeret-nyeret, tidak perlu didorong-dorong, nanti juga akan ketahuan kalau memang ada keterlibatan,” katanya.
Sikap tenang ini memicu polarisasi persepsi publik: apakah ia benar-benar tak bersalah, atau justru strategi defensif untuk meredam spekulasi? Yang tak terbantahkan adalah catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, yang mencatat total aset mendekati Rp50 miliar. Rinciannya mencakup tanah dan bangunan senilai Rp40,39 miliar, kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Lexus LX 570, dan Toyota Fortuner yang bernilai Rp3,26 miliar secara keseluruhan, ditambah aset bergerak Rp1,39 miliar, surat berharga Rp112 juta, serta kas dan setara kas Rp4,79 miliar.
Kenaikan kekayaan yang dramatis ini—terutama di tengah jabatannya di Komisi XI DPR RI yang mengawasi sektor perbankan—membangkitkan keraguan struktural. Komisi tersebut memiliki peran krusial dalam mengendalikan BI dan OJK, lembaga-lembaga yang kini menjadi pusat skandal. Apakah aset-aset ini lahir dari gaji resmi, warisan keluarga, atau aliran dana gelap? Pertanyaan ini menggemakan analisis korupsi sebagai “jebakan kemiskinan” ala Susan Rose-Ackerman, di mana posisi kekuasaan memfasilitasi akumulasi ilegal.

Pemerhati kebijakan publik Bang Regar menilai kasus ini sebagai titik balik bagi integritas nasional. “Jika benar ada indikasi keterlibatan pejabat publik, apalagi jika menyangkut banyak anggota Komisi XI DPR, maka KPK tidak boleh tebang pilih. Praktik korupsi berjamaah harus diberantas tuntas agar tidak menjadi budaya yang merusak integritas bangsa,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi reformasi, termasuk penguatan mekanisme pengawasan CSR melalui audit independen dan integrasi data PPATK dengan KPK secara real-time.
Di tengah hiruk-pikuk ini, kasus CSR BI-OJK bukan hanya cerita korupsi semata, melainkan cerminan sistemik tentang bagaimana dana publik—yang seharusnya memberdayakan masyarakat—berakhir di kantong elit. Saat KPK melangkah lebih dalam, publik menanti: apakah ini akan menjadi kemenangan supremasi hukum, atau sekadar babak baru dalam siklus impunitas politik Indonesia? Hanya waktu, dan keteguhan lembaga, yang akan menjawab.
Pewarta : Indra Saputra