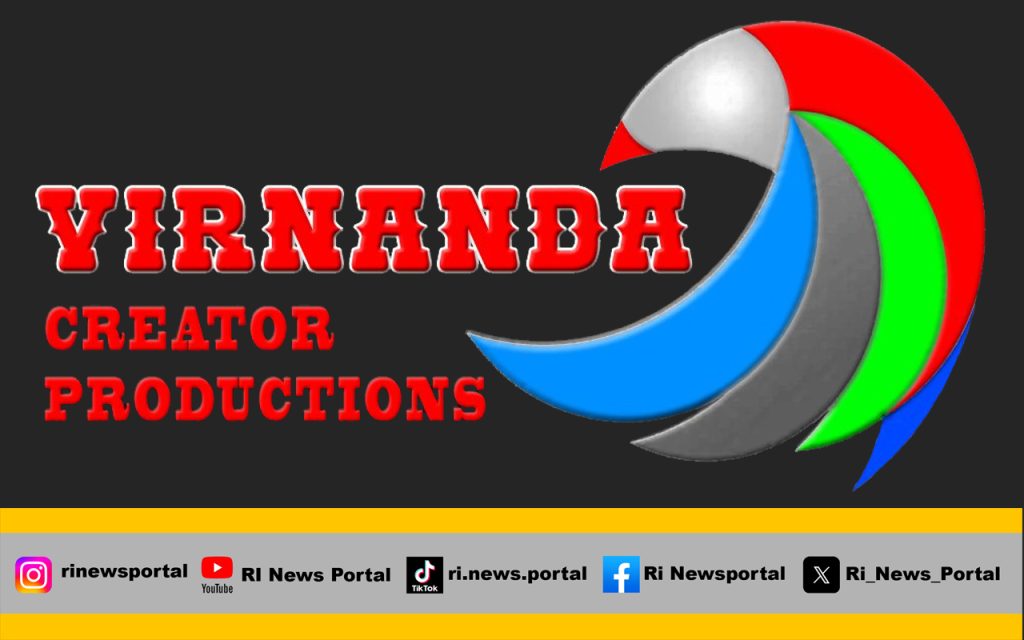RI News Portal. Sulawesi Utara 1 November 2025 – Di bawah langit mendung yang seolah mencerminkan kegelisahan nasibnya, Prof. Ing Mokoginta, mantan guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), kembali menyuarakan jeritannya atas perampasan tanah yang telah merenggut martabatnya selama delapan tahun terakhir. Sebagai akademisi yang pernah mengabdikan puluhan tahun untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, perjuangannya kini lebih mirip dengan perjalanan seorang pengembara di padang pasir hukum yang kering kerontang: penuh harapan palsu, tapi tak kunjung menemukan oasis keadilan.
Pagi ini, di sebuah ruang sederhana di pinggiran ibu kota, Prof. Mokoginta bertemu dengan awak media, matanya yang lelah tapi penuh api semangat menceritakan kisah yang tak henti-hentinya mengguncang nurani. “Saya sudah mengemis keadilan selama delapan tahun. Tanah milik saya di Gogagoman, Kotamobagu, Sulawesi Utara, yang luasnya 1,7 hektar dan didukung Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, dirampas melalui pemalsuan dokumen yang jelas-jelas pesanan. Dan anehnya, meski saya menang dua kali di praperadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peninjauan Kembali (PK), tanah itu belum kembali ke tangan saya,” ujarnya dengan suara bergetar, seolah setiap kata adalah beban yang selama ini dipikul sendirian.
Kasus ini bukan sekadar sengketa lahan biasa. Ia adalah cerminan gelap dari praktik mafia tanah yang merajalela di negeri ini, di mana oknum birokrasi dan elite ekonomi diduga berkolusi untuk merenggut hak-hak rakyat kecil. Polri telah menetapkan sembilan tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan, termasuk nama-nama seperti Welly Mokoginta alias Tiong, Jantje Mokoginta alias Hian, dan Herry Mokoginta alias Kian. Namun, hingga kini, tak satu pun dari mereka ditahan. Malah, salah satu oknum kunci, Maikel Waas—yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Seksi Survei dan Pemetaan—justru naik pangkat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Halmahera Barat. “Ini seperti hukum yang dimainkan seenaknya. Oknum BPN ini sudah jadi tersangka di Mabes Polri, tapi bebas berkeliaran. Apakah ini hadiah atas ‘jasa’ mereka?” tanya Prof. Mokoginta, nada suaranya penuh sindiran pedas.

Lebih jauh, Prof. Mokoginta menuding adanya keterlibatan pihak berpengaruh di balik layar. “Salah satu tersangka, inisial S.M.—Stella Mokoginta, istri pengusaha besar di balik PT Hasrat Abadi—diduga punya tangan panjang yang bisa ‘membeli’ keadilan. Sertifikat palsu itu diterbitkan hanya dalam lima hari kerja, hasil kolusi antara oknum BPN dan terlapor. Ini bukan kebetulan; ini sistematis.” PT Hasrat Abadi, perusahaan yang dikenal luas di sektor transportasi dan pertanian di wilayah timur Indonesia, kini menjadi sorotan karena dugaan keterkaitannya dengan jaringan ini. Meski belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan, tuduhan ini menambah lapisan kompleksitas pada kasus yang telah menyeret delapan tahun perjuangan pengadilan.
Di sela pertemuan itu, hadir juga Jhony Rondonuwu, Ketua Umum Pagar Emas Nusantara (PEN), organisasi masyarakat yang dikenal vokal dalam isu-isu keadilan sosial. Dengan nada tegas, Rondonuwu mengecam apa yang ia sebut sebagai “keadilan yang sangat sadis” di negeri ini. “Apakah keadilan bisa dibeli? Prof. Ing telah mengabdikan hidupnya untuk negara, tapi kini ia diperlakukan seperti ini. Sembilan tersangka, termasuk oknum BPN dan elite pengusaha, berkeliaran bebas. Ada apa sebenarnya? Apakah karena ada orang penting seperti S.M. yang terlibat, sehingga proses hukum mandek?” serunya, seolah mewakili suara rakyat yang muak dengan inkonsistensi penegak hukum.
Rondonuwu bukanlah pendatang baru dalam advokasi semacam ini. Sebagai pemimpin PEN, ia telah lama mengawal isu korupsi agraria, dan hari ini ia menjadikan kasus Prof. Mokoginta sebagai panggung untuk menyoroti kegagalan sistemik. “Hukum terus dipermainkan. Oknum seperti Maikel Waas, yang seharusnya dilepas jabatannya, malah dihadiahi posisi baru. Ini bukan keadilan; ini penghianatan terhadap rakyat,” tambahnya, sambil menyerukan agar Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung.
Kembali ke Prof. Mokoginta, permohonannya kepada Presiden terdengar seperti seruan darurat dari seorang yang telah kehilangan segalanya. “Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya mohon Bapak melihat apa yang terjadi pada saya. Delapan tahun saya mengemis, dari pengadilan ke polisi, dari Polda Sulut ke Mabes Polri. Jangan biarkan rakyat terus menderita, diinjak-injak oleh oknum yang mengatasnamakan institusi kepolisian dan birokrasi. Ini bukan hanya kasus saya; ini soal martabat bangsa.” Air matanya menetes saat menyebutkan bagaimana tanah warisan itu bukan hanya aset, tapi simbol perjuangan hidupnya sebagai ilmuwan yang pernah berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional.
Kasus ini menggema lebih luas dari sekadar satu individu. Di tengah maraknya mafia tanah yang merampas aset pemerintah dan rakyat jelata, perjuangan Prof. Mokoginta menjadi metafora bagi ketidakpastian hukum agraria di Indonesia. Mahasiswa, ormas adat seperti Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), dan kelompok masyarakat sipil telah berulang kali menggelar aksi solidaritas, menuntut intervensi dari tingkat tertinggi. Namun, delapan tahun berlalu, dan tanah itu tetap di tangan yang salah.
Apakah jeritan ini akan didengar? Atau akankah Prof. Mokoginta terus menjadi “pengemis keadilan” di negeri yang katanya berdaulat hukum? Saat matahari terbenam di ufuk Jakarta, pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban dari mereka yang berwenang. Seperti kata Rondonuwu, “Keadilan bukan barang dagangan. Ia adalah hak setiap warga negara, termasuk seorang profesor yang telah memberi segalanya untuk bangsa ini.”
Pewarta : Marco Kawulusan