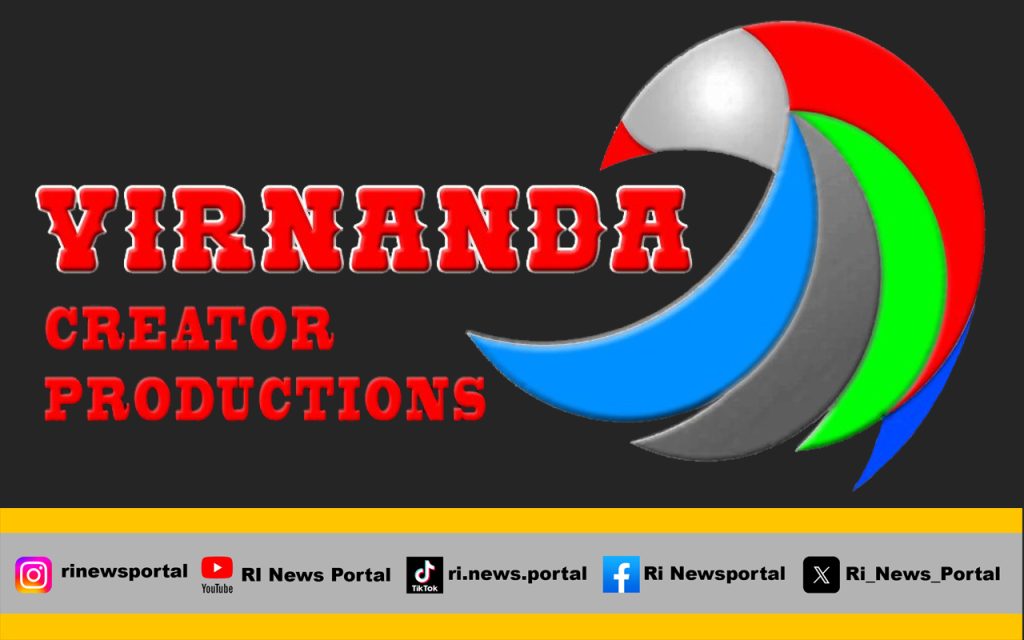RI NewsPortal. Teheran, 18 Januari 2026 – Pidato Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada akhir pekan lalu menjadi titik puncak baru dalam konfrontasi retorika dengan Amerika Serikat. Dalam penyampaiannya yang disiarkan secara nasional, Khamenei secara tegas menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai “penjahat” atas dukungannya terhadap gelombang protes domestik yang melanda Iran sejak akhir Desember tahun lalu. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan polarisasi mendalam antara kedua negara, tetapi juga mengungkap dinamika internal Iran yang rapuh di tengah tekanan ekonomi dan politik.
Protes yang bermula dari ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi nasional dengan cepat berkembang menjadi gerakan luas yang menantang otoritas pemerintahan. Penindakan keras oleh aparat keamanan telah menimbulkan korban jiwa signifikan, dengan estimasi independen menyebutkan ribuan nyawa melayang—angka yang jauh melampaui kerusuhan serupa dalam sejarah kontemporer Iran. Khamenei, dalam argumennya, membalik narasi dengan menyalahkan demonstran sebagai agen eksternal yang didukung AS, bahkan mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur publik dan korban jiwa. Ia menekankan bahwa senjata api yang digunakan dalam kerusuhan berasal dari impor asing, meski tanpa merinci sumbernya.
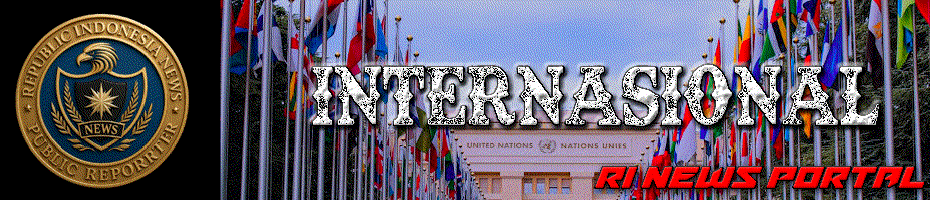
Di sisi lain, respons Trump datang cepat dan tajam. Dalam wawancara eksklusif, presiden AS tersebut menyerukan perubahan kepemimpinan di Iran, menyebut rezim saat ini sebagai penyebab utama penderitaan rakyatnya. Trump juga menyentuh isu eksekusi massal yang sempat menjadi sorotan, dengan nada yang sempat melunak saat mengapresiasi pembatalan hukuman terhadap ratusan tahanan. Namun, nada tersebut segera berganti menjadi ancaman implisit bahwa Washington akan bertindak jika kekerasan berlanjut. Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa AS melihat protes Iran sebagai peluang strategis untuk melemahkan pengaruh Teheran di kawasan Timur Tengah.
Dari perspektif akademis, eskalasi ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pola historis hubungan Iran-AS pasca-Revolusi 1979. Konflik ideologis antara prinsip kedaulatan anti-imperialis Iran dan doktrin intervensi AS sering kali memanfaatkan isu domestik sebagai alat geopolitik. Analis hubungan internasional mencatat bahwa dukungan verbal Trump terhadap pengunjuk rasa—meski tanpa komitmen militer langsung—mencerminkan strategi “tekanan maksimum” yang diwarisi dari masa jabatan sebelumnya, di mana sanksi ekonomi digunakan untuk memicu perubahan rezim dari dalam.
Baca juga : Upaya Diplomasi Ukraina di Washington Berlangsung di Tengah Eskalasi Serangan Energi Rusia
Sementara itu, situasi di lapangan menunjukkan tanda-tanda de-eskalasi sementara. Akses internet yang sempat diputus total mulai pulih secara parsial, memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan meski dengan keterbatasan. Tidak ada laporan kerusuhan baru di ibu kota, dan kehidupan sehari-hari tampak normal kembali. Namun, tuduhan saling lempar antara Teheran dengan Washington dan sekutunya terus memanaskan narasi resmi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam komunikasi diplomatik baru-baru ini, menegaskan bahwa campur tangan asing menjadi faktor utama destabilisasi.

Krisis ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang masa depan stabilitas regional. Dengan Iran mempertahankan sikap defensif non-perang sambil mengejar akuntabilitas internal dan eksternal, serta AS yang tampak ragu antara intervensi langsung dan dukungan jarak jauh, risiko salah kalkulasi tetap tinggi. Pengamat menilai bahwa resolusi jangka panjang bergantung pada dialog multilateral yang melibatkan aktor regional, meski prospeknya saat ini masih suram di tengah polarisasi yang semakin dalam.
Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan apakah ketegangan ini mereda menjadi diplomasi senyap atau justru memicu babak baru konfrontasi.
Pewarta : Setiawan Wibisono