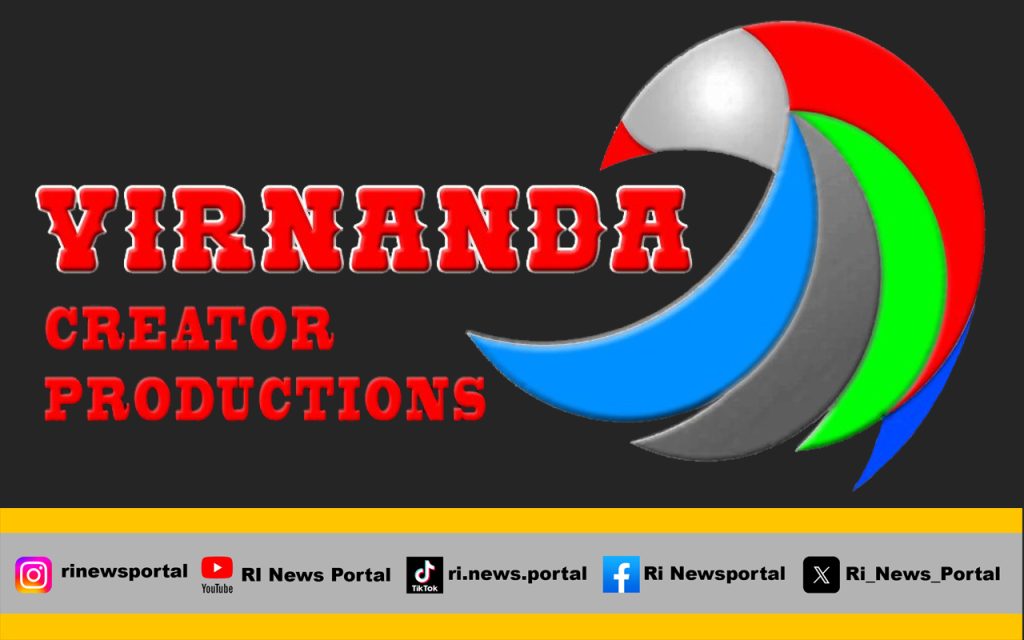RI News Portal. NUUK, Greenland — Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di wilayah Arktik, pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland pada pertengahan Januari 2026 menegaskan adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai masa depan pulau terbesar di dunia itu. Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan konkret, pertemuan tersebut membuka jalan bagi pembentukan kelompok kerja untuk membahas kekhawatiran keamanan, sementara Presiden Donald Trump terus menekankan pentingnya akuisisi Greenland bagi kepentingan nasional AS. Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, implikasi strategis, dan respons internasional terhadap isu yang semakin memanaskan dinamika aliansi transatlantik.
Pertemuan di Gedung Putih pada 14 Januari 2026 melibatkan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dari pihak AS, serta Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan rekannya dari Greenland, Vivian Motzfeldt. Rasmussen menggambarkan diskusi sebagai “terbuka dan konstruktif” namun menekankan adanya “ketidaksepakatan fundamental” atas keinginan Trump untuk “menguasai” Greenland. Ia menambahkan bahwa kelompok kerja yang dibentuk harus fokus pada penanganan kekhawatiran keamanan AS sambil menghormati batas-batas kedaulatan Denmark, yang mencakup penolakan tegas terhadap ide penjualan atau pengambilalihan. Di sisi lain, Gedung Putih menyebut pembicaraan lanjutan sebagai “diskusi teknis mengenai perjanjian akuisisi,” yang menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dari pihak AS.

Ambisi Trump terhadap Greenland bukanlah hal baru; ia pertama kali menyuarakannya pada 2019 selama masa jabatan pertamanya, dengan alasan strategis seperti akses terhadap sumber daya alam langka, rute pelayaran Arktik yang terbuka akibat perubahan iklim, dan penguatan posisi militer melawan pengaruh Rusia serta Cina di wilayah kutub. Dalam konteks akademis, minat ini dapat dilihat sebagai bagian dari doktrin “America First” yang menekankan ekspansi teritorial untuk mengamankan rantai pasok global, terutama mineral tanah jarang yang krusial bagi teknologi hijau dan pertahanan. Studi dari lembaga riset seperti Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa Arktik semakin menjadi arena kompetisi besar, di mana pencairan es membuka peluang ekonomi sekaligus risiko konflik. Namun, pendekatan AS ini menuai kritik karena berpotensi melanggar prinsip hukum internasional, termasuk hak penentuan nasib sendiri bagi penduduk Greenland yang mayoritas Inuit, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.
Respons Eropa terhadap situasi ini menunjukkan solidaritas yang kuat. Sehari sebelum pertemuan, Denmark mengumumkan peningkatan kehadiran militer di Greenland, diikuti oleh kedatangan pasukan simbolis dari negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Belanda. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyatakan bahwa langkah ini bertujuan membangun kehadiran permanen melalui rotasi pasukan NATO, sebagai sinyal bahwa keamanan Arktik dapat dijaga secara kolektif tanpa perlu pengambilalihan oleh satu negara. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan, “Greenland bukan untuk dijual,” sambil menyambut dialog diplomatik sebagai jalan keluar. Dari perspektif geopolitik, gerakan ini mencerminkan kekhawatiran Eropa atas potensi disintegrasi NATO, di mana ambisi AS bisa merusak kepercayaan antar-aliansi, mirip dengan ketegangan era Perang Dingin ketika AS pernah menawarkan pembelian Greenland pada 1946.
Baca juga : Inisiatif Pembangunan Hunian Layak di Papua: Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan
Secara akademis, isu ini menyoroti paradoks dalam hubungan transatlantik: Di satu sisi, AS melihat Greenland sebagai aset vital untuk menghadapi ancaman dari aktor non-Barat, seperti ekspansi Rusia di Arktik yang dikritik sebagai “agenda anti-Rusia” oleh Kedutaan Rusia di Brussels. Di sisi lain, pendekatan unilateral Trump berisiko mengalienasi sekutu, yang justru memperkuat narasi bahwa Arktik harus tetap zona perdamaian melalui kerjasama multilateral. Penelitian dari Arctic Institute menekankan bahwa perubahan iklim mempercepat perebutan sumber daya, di mana Greenland menyimpan cadangan mineral senilai triliunan dolar, termasuk uranium dan litium, yang bisa menjadi katalisator konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Penduduk setempat di Nuuk, ibu kota Greenland, menyampaikan campuran kecemasan dan harapan. Seorang warga berusia 21 tahun, Maya Martinsen, menyebut dukungan Nordik sebagai “penenang” di tengah kekhawatiran atas motif ekonomi di balik klaim keamanan. Sementara itu, anggota parlemen Greenland Juno Berthelsen menyarankan alternatif seperti kemitraan AS dalam pembangunan penjaga pantai lokal, yang bisa menciptakan lapangan kerja tanpa mengorbankan kedaulatan. Di Washington, Rasmussen juga bertemu senator bipartisan, yang menyuarakan kekhawatiran atas potensi penggunaan kekuatan militer oleh Trump, mendorong pendekatan kolaboratif untuk keamanan Arktik.

Trump sendiri, dalam pernyataan singkat, mengatakan, “Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Saya pikir sesuatu akan berhasil.” Meskipun dialog berlanjut, situasi ini menggarisbawahi tantangan bagi tatanan internasional pasca-Perang Dingin, di mana ambisi nasionalis bertabrakan dengan norma multilateralisme. Bagi Greenland, yang sedang mengejar kemerdekaan lebih besar dari Denmark, isu ini bisa menjadi katalisator untuk perubahan status quo, sementara bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa Arktik bukan lagi periferal, melainkan pusat perebutan kekuasaan global di abad ke-21.
Pewarta : Setiawan Wibisono