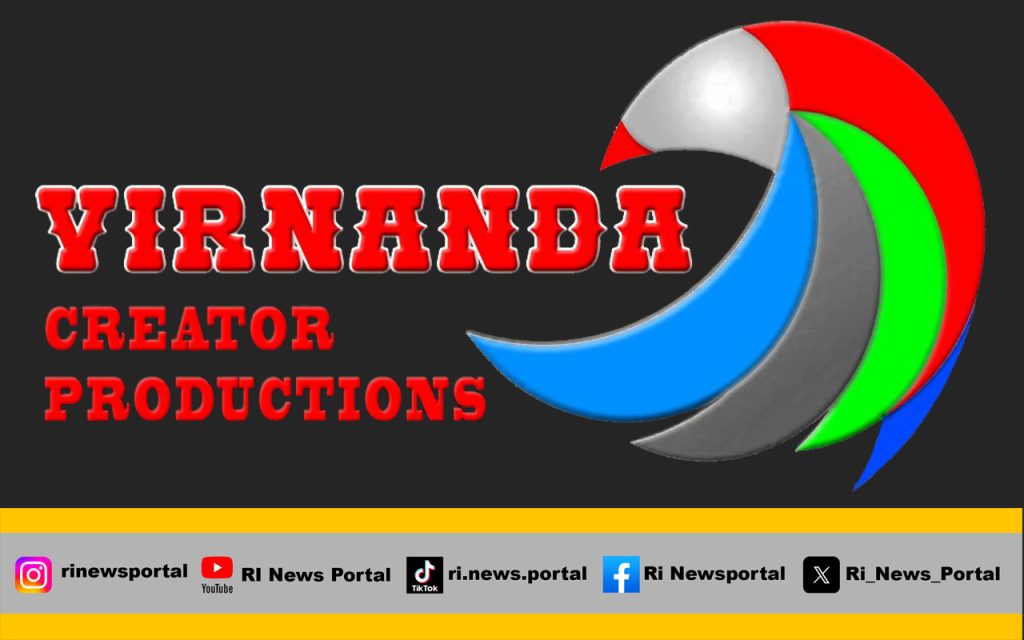RI News Portal. Semarang– Angin sore bertiup pelan di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro, yang kala itu lebih suka hidup sederhana di luar keraton, duduk di serambi rumah sambil memandang sawah yang mulai menguning. Hatinya gelisah, bukan karena urusan dunia, tetapi karena tanah leluhurnya hendak dilalui proyek jalan yang dipaksakan Belanda.
“Apakah kita harus diam saat tanah warisan para leluhur diinjak-injak?” ucapnya lirih pada Kiai Mojo, sahabat dan penasihat spiritualnya.
“Tidak, Pangeran. Rakyat sudah terlalu lama menanggung beban. Mungkin inilah saatnya jihad melawan penindasan,” jawab Kiai Mojo dengan suara mantap.
Beberapa hari kemudian, bendera perlawanan dikibarkan. Ribuan rakyat dari Bagelen, Banyumas, hingga Kediri berbondong-bondong datang membawa senjata seadanya: pedang, tombak, bahkan bambu runcing. Mereka percaya, bersama Diponegoro, mereka akan menuntut keadilan.

Tanggal 20 Juli 1825 menjadi awal dari kobaran besar. Pasukan Diponegoro menyerang pos Belanda di dekat Yogyakarta. Asap membumbung, dentuman senjata api Belanda terdengar bersahutan dengan teriakan takbir para laskar.
“Jangan takut pada peluru mereka!” seru Pangeran Diponegoro di tengah medan. “Allah bersama kita, bersama orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran!”
Belanda kaget. Dalam hitungan bulan, perlawanan Diponegoro menyebar ke hampir seluruh Jawa. Belanda mengirim ribuan tentara, namun taktik gerilya yang dipimpin para panglima Diponegoro membuat mereka kewalahan. Jalan-jalan menuju kota terputus, logistik Belanda terhambat, dan beberapa benteng kolonial berhasil direbut.
Namun perang selalu membawa duka. Rakyat banyak yang meninggalkan sawah dan ladang, hidup di hutan dan gua untuk menghindari kejaran tentara kolonial. Dalam keheningan malam, Diponegoro sering duduk termenung.
“Berapa lama lagi kita harus bertahan, Kiai?” tanya Diponegoro pada Kiai Mojo.
“Selama darah kita masih mengalir, Pangeran. Perlawanan ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kelak.”
Melihat kekuatan Diponegoro yang tak kunjung padam, Jenderal De Kock merancang benteng stelsel—membangun benteng kecil di setiap desa untuk memutus gerakan laskar. Sedikit demi sedikit, kekuatan Diponegoro terdesak. Beberapa panglima gugur, di antaranya Sentot Prawirodirjo yang setia berperang hingga akhir.
Baca juga : Refleksi 200 Tahun Perang Jawa: Menbud Fadli Zon Tekankan Jati Diri Bangsa
Musim kemarau tahun 1829 menjadi masa tersulit. Rakyat kekurangan makanan, penyakit mulai menyebar, dan pengkhianatan terjadi di beberapa pihak. Meski begitu, semangat Diponegoro tak surut.
“Kita boleh kalah di medan perang,” ujarnya pada para pengikutnya, “tapi jangan pernah kalah dalam iman dan keyakinan.”
Tahun 1830, Belanda menawarkan perundingan damai. Di Magelang, Pangeran Diponegoro datang dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan rakyat. Namun, itu hanyalah siasat licik.
Ketika pintu ruang perundingan tertutup, De Kock memberi tanda pada tentaranya.
“Maafkan aku, Pangeran. Ini perintah negeri kami,” ujar De Kock dengan dingin.
Diponegoro ditangkap tanpa sempat melawan. Dari balik jendela penjara, ia menatap langit Magelang, seakan berbicara kepada rakyatnya:
“Perjuangan ini belum berakhir. Suatu hari nanti, bangsa ini akan merdeka.”
Meski diasingkan ke Manado, lalu Makassar, nama Diponegoro justru semakin harum. Perang Jawa yang menelan korban ratusan ribu jiwa menjadi saksi bahwa semangat perlawanan rakyat Nusantara tak bisa dipadamkan. Kini, Pangeran Diponegoro dikenang bukan hanya sebagai pahlawan perang, tetapi sebagai simbol keteguhan hati, iman, dan keberanian melawan ketidakadilan.
Penulis : Anjar Bramantyo