
RI News Portal. Jakarta, 10 Oktober 2025 – Dalam sebuah vonis tuntutan yang mencolok di tengah maraknya kontroversi selebriti di ranah digital, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari Kamis lalu (9/10/2025) mengajukan hukuman pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap artis Nikita Mirzani. Kasus ini, yang bermula dari siaran langsung di platform TikTok pada November 2024, kini menjadi sorotan bukan hanya sebagai perkara pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tetapi juga sebagai cerminan tantangan hukum di era konten viral.
Nikita Mirzani, yang lahir pada 1986 dan dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan di media sosial, didakwa atas pelanggaran Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 369 KUHP terkait pemerasan disertai ancaman, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Tuntutan ini dibacakan di ruang sidang Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Khairul Soleh. “Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut,” tegas salah satu jaksa dalam amar tuntutannya, menekankan kerugian materiil dan moral yang dialami korban.
Kasus ini berakar pada dinamika kompleks antara ekspresi digital dan batas hukum. Pada November 2024, Nikita melakukan live streaming di TikTok yang secara tidak langsung menyentil reputasi bisnis kecantikan milik dr. Reza Gladys, pemilik PT Glafidsya RMA Group. Pernyataan Nikita, yang dianggap merugikan, memicu respons dari Reza yang berupaya menyelesaikan secara damai. Namun, komunikasi selanjutnya justru melahirkan dugaan permintaan uang sebesar Rp5 miliar dari pihak Nikita agar konten negatif dihentikan—sebuah tuntutan yang kemudian diinterpretasikan sebagai pemerasan.

Reza, merasa terintimidasi, segera melaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyelidikan mengungkap peran asisten Nikita, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, dalam transaksi tersebut, yang kemudian berkembang menjadi dakwaan TPPU. Dari perspektif akademis, kasus ini mengilustrasikan bagaimana konten media sosial—yang sering kali bersifat impulsif—dapat bertransformasi menjadi alat pemerasan, sebagaimana dianalisis dalam studi hukum digital oleh pakar seperti Dr. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia. “UU ITE, meski dimaksudkan melindungi dari hoaks, kerap digunakan untuk membungkam kritik, menciptakan grey area antara kebebasan berpendapat dan ancaman ekonomi,” ujar Juwana
Berbeda dengan laporan media konvensional yang fokus pada kronologi faktual, analisis ini menyoroti pola serupa di kasus-kasus sebelumnya, seperti tuntutan terhadap influencer lain pada 2023 yang melibatkan smear campaign di Instagram. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan peningkatan 45% kasus UU ITE terkait reputasi bisnis sejak 2022, menandakan urgensi reformasi undang-undang untuk membedakan antara kritik sah dan pemerasan terstruktur.
JPU tidak segan memaparkan delapan poin yang memberatkan Nikita, termasuk sikapnya yang dinilai tidak kooperatif selama persidangan—berbelit-belit dalam keterangan dan menolak pengakuan perbuatan. “Terdakwa telah merusak nama baik korban, meresahkan masyarakat luas, dan menikmati hasil kejahatan,” papar jaksa, merujuk pada riwayat hukum Nikita sebelumnya yang mencakup kasus serupa. Satu-satunya poin meringankan adalah tanggung jawabnya sebagai ibu tunggal dengan tiga anak, yang menurut jaksa tidak cukup untuk mengurangi bobot tuntutan.
Baca juga : KPK Dalami Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji 2023-2024: Fokus pada Katering, Logistik, dan Jual-Beli Kuota
Permintaan agar Nikita tetap ditahan selama proses berlanjut juga ditekankan, dengan alasan menjaga integritas peradilan. Dari sudut pandang kriminologi, ini mencerminkan pendekatan retributif hukum Indonesia yang semakin ketat terhadap pelaku “white-collar crime” di ranah digital, sebagaimana dibahas dalam jurnal Hukum dan Pembangunan edisi terbaru. Peneliti dari Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (LK2I) menambahkan bahwa tuntutan sebesar ini bisa menjadi preseden, mendorong platform seperti TikTok untuk lebih proaktif dalam moderasi konten, meski berisiko membatasi kebebasan ekspresi.
Di luar ruang sidang, Nikita tampil dengan ketenangan yang kontras. “Tuntutannya 11 tahun, enggak ada masalah. Itu kan hak jaksa, yang penting tahap ini selesai. Nanti giliran saya pledoi minggu depan,” katanya kepada wartawan, sambil tersenyum ringan. Sidang pembacaan nota pembelaan dijadwalkan pada 16 Oktober 2025, di mana tim kuasa hukumnya diharapkan membongkar narasi jaksa dengan bukti kontra, termasuk konteks komunikasi yang mungkin bersifat negosiasi damai.
Optimisme Nikita ini bukan tanpa dasar. Pengamat hukum seperti Prof. Todung Mulya Lubis menilai bahwa pleidoi yang kuat bisa menurunkan tuntutan, mengingat bukti TPPU sering kali bergantung pada jejak keuangan yang rumit. “Kasus ini bukan sekadar pidana, tapi ujian bagi sistem peradilan untuk menyeimbangkan hak korban dengan prinsip praduga tak bersalah,” tegas Lubis.
Lebih dari sekadar nasib satu artis, kasus Nikita Mirzani membuka diskusi mendalam tentang etika konten kreator di Indonesia. Dengan 170 juta pengguna media sosial aktif (data We Are Social 2025), insiden seperti ini berpotensi mengubah lanskap hiburan digital. Apakah ini akan mendorong self-censorship di kalangan influencer, atau justru memperkuat advokasi reformasi UU ITE yang lebih proporsional?
Sementara menunggu putusan majelis hakim, kasus ini tetap menjadi pengingat: di balik gemerlap layar, batas antara opini dan kriminalitas semakin tipis.
Pewarta : Vie
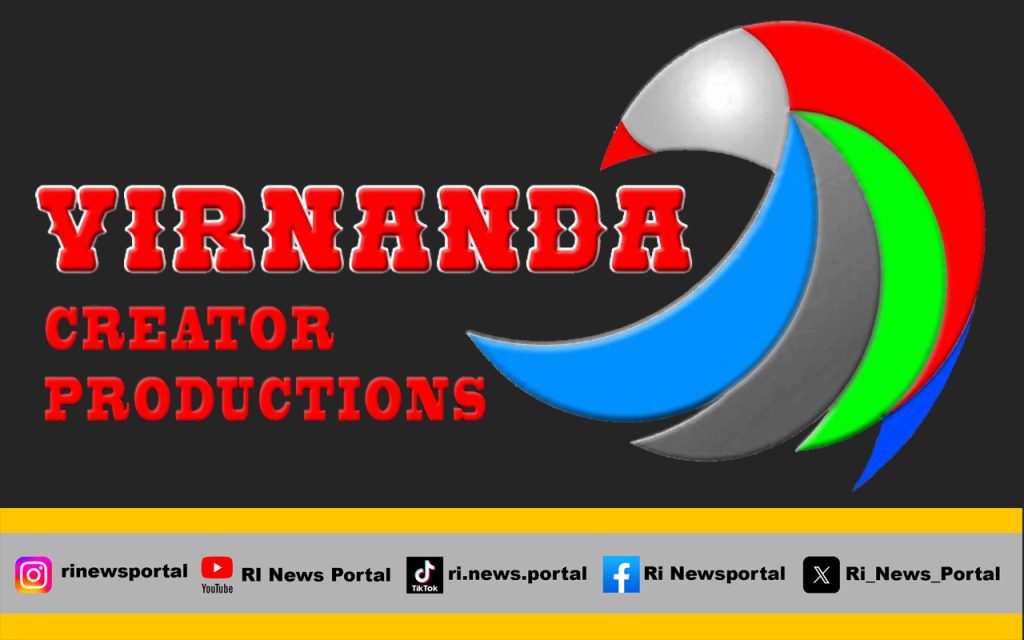





Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Absen akhir pekan pagi hari ini Sabtu. Kalau kau mampu bangun pagi untuk dunia, maka bangunlah lebih awal untuk akhiratmu. Memaafkan itu indah. Jangan biarkan dendam membunuhmu. Ujian itu bagian dari hidup sikapi dengan sabar karena dari situ kita menjadi lebih kuat. Salam sejahtera sehat sukses selalu dan satu pena untuk para wartawan jurnalis kabiro kaperwil beserta pimpinan redaksi Républik Indonésia News Portal terimakasih.