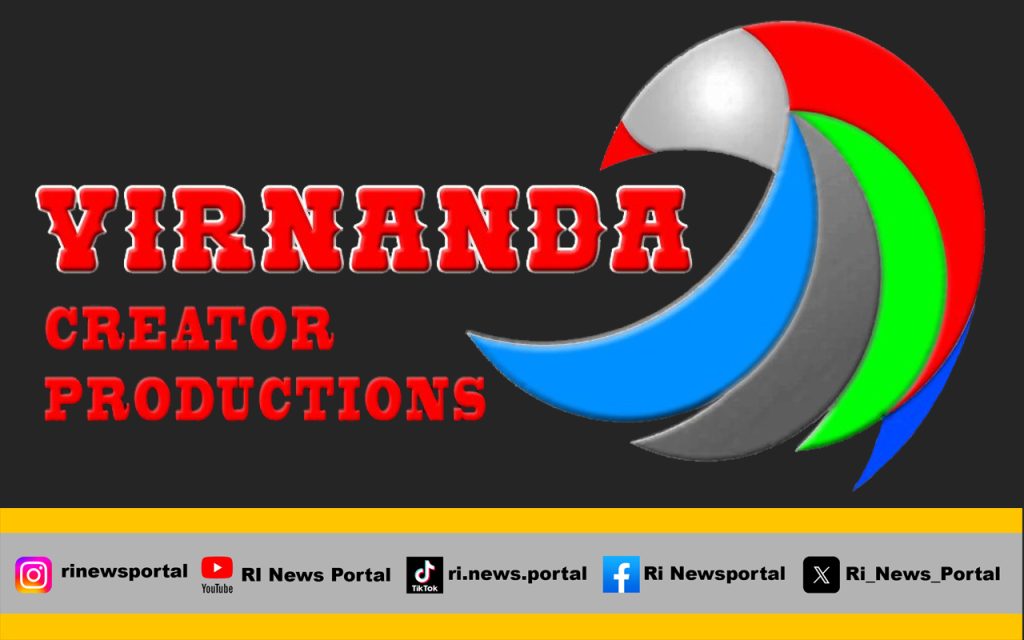RI News Portal. Jakarta, 30 September 2025 – Di tengah hiruk-pikuk gelombang protes sosial yang melanda ibu kota sejak awal bulan ini, sebuah insiden tragis menyoroti sisi gelap dari amarah kolektif: bukan hanya kerusakan fisik, tapi luka psikis yang mendalam. Surya Utama, lebih dikenal sebagai Uya Kuya—anggota DPR RI Fraksi PAN sekaligus figur publik—kembali ke rumahnya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, hari ini. Apa yang ditemuinya bukan sekadar puing-puing barang berharga yang dirampas, melainkan coretan-coretan hinaan kasar di dinding yang menyasar istri dan anak-anaknya. “Ini bukan soal harta; ini soal martabat keluarga yang tak bersalah,” ungkap Uya dengan suara parau, seperti yang ia bagikan melalui unggahan Instagram pribadinya (@king_uyakuya).
Insiden penjarahan rumah Uya pada 30 Agustus lalu—yang kini telah menjerat 15 tersangka menurut keterangan terbaru dari Polres Metro Jakarta Timur—berawal dari sebuah video lama yang dimanipulasi. Rekaman Uya berjoget di lingkungan parlemen, yang sebenarnya berasal dari momen ringan bertahun-tahun lalu, diedit dan diberi narasi provokatif seolah-olah ia meremehkan rakyat kecil di tengah wacana kenaikan gaji DPR. Manipulasi ini menyebar liar di media sosial, memicu gelombang kemarahan yang meluas ke residensi anggota DPR lain seperti Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, dan Eko Patrio. Namun, di balik euforia massa yang merasa “mengambil kembali hak”, tersimpan dinamika psikologis yang jarang dibahas: bagaimana fitnah verbal menjadi senjata yang lebih mematikan daripada palu godam.

Menurut Dr. Rina Susanti, psikolog sosial dari Universitas Indonesia yang mengkhususkan diri pada trauma kolektif, kasus seperti ini mencerminkan fenomena “dehumanisasi sekunder”. “Ketika amarah massa ditargetkan pada simbol kekuasaan, korban sering kali ‘dibuat tak manusiawi’—bukan lagi individu, tapi target abstrak. Yang lebih parah, ekstensi ke keluarga menciptakan efek domino: rasa aman dasar terganggu, memicu gangguan stres pasca-trauma (PTSD) jangka panjang pada anak-anak yang tak terlibat,” jelas Dr. Susanti dalam wawancara eksklusif dengan Akademia Insight. Studi yang dipublikasikan di Journal of Social Psychology tahun 2024 menunjukkan bahwa 68% korban kekerasan verbal keluarga mengalami peningkatan kecemasan kronis, terutama jika hinaan tersebut bersifat personal dan publik seperti coretan di dinding rumah.
Uya, yang dikenal sebagai presenter karismatik dengan segudang pengalaman di layar kaca, tampak hancur saat menelusuri reruntuhan rumahnya pagi ini. Barang elektronik, surat-surat penting, hingga foto-foto keluarga lenyap atau hancur—termasuk majalah berisi potret putrinya, Cinta Kuya, yang kini berserakan di halaman depan. Tapi yang paling menusuk adalah pesan-pesan kasar seperti “Keluarga lo pantas menderita juga” dan “Anak lo bakal bayar dosa bapaknya”, yang ditulis dengan cat semprot hitam di tembok putih rumahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Uya merekam dirinya di depan puing-puing itu, suaranya bergetar menahan isak. “Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apa pun. Marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya,” katanya, seperti dikutip dari video Instagram-nya yang langsung viral, ditonton jutaan kali dalam hitungan jam.
Baca juga : Program Waste to Energy: Solusi Inovatif Kurangi Emisi dan Ciptakan Energi Terbarukan
Permohonan pilu itu bukan sekadar luapan emosi; ia mencerminkan dilema etis yang lebih luas dalam dinamika sosial saat ini. Uya menekankan, “Saya siap tanggung konsekuensi atas apa pun yang saya lakukan sebagai wakil rakyat. Tapi apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya?” Astrid Kuya, istrinya, yang juga turut hadir di lokasi, menambahkan bahwa rumah itu bukan hanya aset material, tapi “tempat di mana kenangan dibangun—dari ulang tahun anak hingga Natal keluarga”. Kehilangan itu, kata Dr. Susanti, bisa memicu “kehilangan identitas kolektif”, di mana keluarga merasa terasing dari lingkungan yang dulu aman.
Secara akademis, kasus ini menjadi studi kasus berharga tentang “kekerasan simbolik” dalam era digital, sebagaimana diuraikan oleh Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang kekuasaan. Video manipulatif yang memicu aksi ini bukan kebetulan; ia bagian dari pola provokasi yang memanfaatkan algoritma media sosial untuk memperbesar echo chamber. Sebuah analisis dari Pusat Studi Media Digital Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa konten semacam itu meningkat 40% selama periode protes sosial di Indonesia tahun 2025, sering kali didorong oleh akun anonim yang lolos dari verifikasi. “Ini bukan lagi soal politik semata, tapi kegagalan kolektif dalam verifikasi fakta. Massa merasa berkuasa, tapi akhirnya menciptakan korban tak berdosa,” tambah Dr. Andi Wijaya, peneliti media dari UGM.

Hingga sore ini, polisi masih mengembangkan kasus dengan fokus pada provokator utama, sementara karangan bunga simpati dari warga dan selebriti mulai berdatangan ke depan rumah Uya—sebuah kontras ironis dengan puing-puing di dalamnya. Uya sendiri menyatakan niatnya untuk restorative justice terhadap sebagian pelaku, terutama ibu-ibu yang terlibat karena kemiskinan, tapi tegas menolak pengampunan bagi yang menargetkan keluarganya. “Saya maafkan yang mencuri karena lapar, tapi hinaan ke anak saya? Itu tak termaafkan,” tegasnya.
Insiden ini mengingatkan kita pada urgensi pendidikan literasi digital dan empati sosial. Di saat amarah mudah dibangkitkan oleh klik mouse, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana kita melindungi yang lemah dari badai opini? Uya Kuya, dengan permohonannya yang menyentuh, mungkin telah membuka babak refleksi nasional—bukan sebagai korban politik, tapi sebagai ayah yang berjuang demi martabat keluarga.
Pewarta : Vie