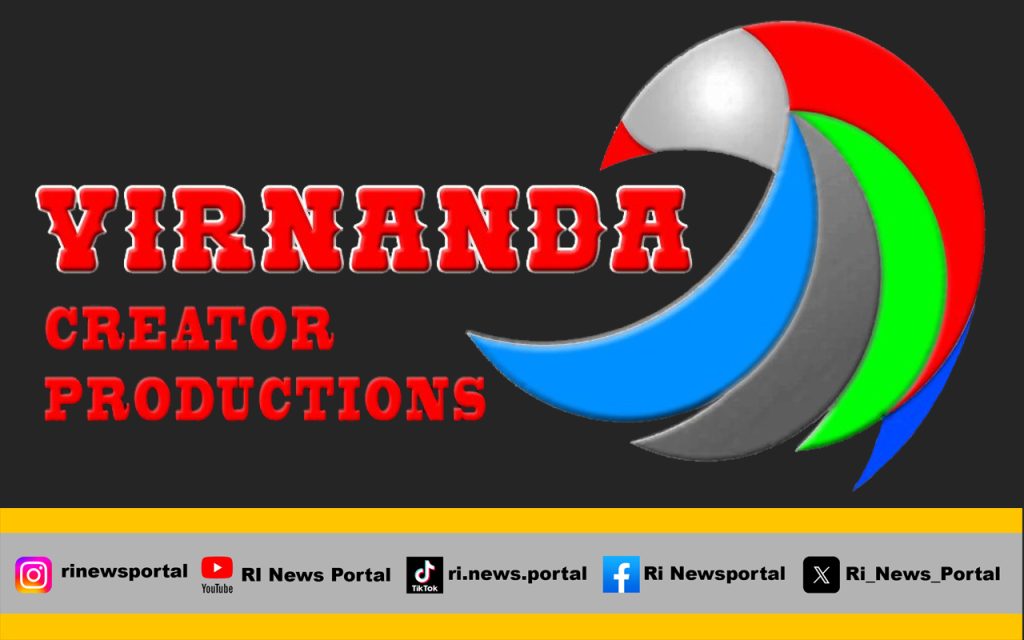RI News Portal. London – Di tengah musim dingin yang dingin, Iran sedang diguncang oleh gelombang protes terbesar sejak revolusi 1979, yang kini memasuki hari ke-16 sejak akhir Desember 2025. Ribuan warga dari berbagai provinsi turun ke jalan, awalnya dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, namun dengan cepat berubah menjadi tuntutan perubahan sistemik terhadap teokrasi Islam yang dipimpin Ayatollah Ali Khamenei. Rezim menghadapi tantangan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan korban tewas mencapai ratusan akibat penindakan keamanan, sementara isolasi komunikasi nasional semakin memperburuk ketidakpastian.
Protes ini dimulai di pasar-pasar utama Tehran, di mana pedagang dan pemilik toko memprotes anjloknya nilai rial yang mencapai rekor terendah 1,42 juta per dolar AS. Keputusan bank sentral untuk menghentikan subsidi dolar murah bagi importir menyebabkan lonjakan harga barang pokok seperti minyak goreng dan daging ayam, bahkan membuat beberapa produk hilang dari rak toko. Kemarahan ini dengan cepat menyebar ke lebih dari 180 kota di seluruh 31 provinsi, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk bazaari—kelompok pedagang tradisional yang historically telah menjadi pendukung setia republik Islam. Arang Keshavarzian, profesor studi Timur Tengah di New York University, menekankan peran historis bazaari: “Selama lebih dari 100 tahun sejarah Iran, bazaari telah menjadi aktor kunci dalam semua gerakan politik utama… Banyak pengamat percaya bahwa bazaari adalah yang paling setia terhadap Republik Islam.” Namun, kini mereka bergabung dengan demonstran yang meneriakkan slogan seperti “Mati untuk Khamenei,” menandakan erosi dukungan basis tradisional rezim.

Respons pemerintah terhadap protes ini semakin represif. Otoritas telah memberlakukan pemadaman komunikasi nasional sejak Kamis lalu, memutus akses ke dunia luar dan menyulitkan verifikasi informasi independen. Jaksa Tehran Ali Salehi mengumumkan bahwa beberapa demonstran bisa menghadapi hukuman mati atas tuduhan “moharebeh” atau perang melawan Tuhan, sementara setidaknya 96 pengakuan paksa telah disiarkan oleh media negara. Presiden Masoud Pezeshkian, seorang reformis dengan kewenangan terbatas di bawah Khamenei, menyalahkan “teroris asing” atas kekacauan, termasuk pembakaran situs-situs budaya, dan menghubungkannya dengan perang 12 hari melawan Israel tahun lalu. Khamenei sendiri mendesak persatuan nasional dan memperingatkan musuh luar, termasuk Presiden AS Donald Trump, untuk fokus pada masalah domestik mereka sendiri. Sementara itu, rezim menggelar rapat umum pro-pemerintah di Lapangan Enqelab Tehran, dihadiri puluhan ribu orang, sebagai upaya menunjukkan kekuatan dan meredam narasi oposisi. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa Iran sedang menghadapi perang empat front: ekonomi, psikologis, militer melawan AS dan Israel, serta melawan terorisme.
Dari perspektif internasional, protes ini menarik perhatian global, terutama setelah korban tewas mencapai 648 orang, termasuk sembilan anak di bawah umur, menurut Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia—angka yang kemungkinan lebih tinggi karena pemadaman informasi. Negara-negara seperti Jerman dan Kanada mengecam penindasan, sementara AS di bawah Trump mengancam intervensi militer jika kekerasan terhadap demonstran berlanjut. Trump menyatakan bahwa militer AS sedang mempertimbangkan “opsi kuat,” meskipun ia lebih memilih diplomasi setelah Iran menyatakan kesiapan bernegosiasi berdasarkan saling hormat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan keterbukaan saluran komunikasi dengan utusan AS Steve Witkoff. Kelemahan regional Iran semakin terlihat setelah serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir dan proxy seperti Hizbullah dan Hamas tahun lalu, yang menyusutkan stok rudal dan pertahanan udara. Sekutu seperti Rusia sibuk dengan perang Ukraina, sementara China hanya menyatakan harapan stabilitas tanpa intervensi langsung.
Secara akademis, protes ini mencerminkan siklus berulang ketidakpuasan di Iran, di mana penindasan negara membatasi oposisi terorganisir, namun ledakan spontan terjadi ketika batas toleransi terlampaui—seperti penegakan jilbab atau inflasi menghancurkan. Dina Esfandiary, pakar ekonomi Timur Tengah dari Bloomberg, menggambarkan situasi sebagai “titik didih” akibat kelelahan masyarakat: “Saya mengantisipasi bahwa Republik Islam seperti sekarang tidak akan bertahan hingga 2027. Saya benar-benar percaya akan ada perubahan.” Keshavarzian menambahkan bahwa tidak ada pemimpin Iran yang memiliki cetak biru untuk keluar dari krisis, dan satu-satunya alat rezim adalah paksaan: “Segmen besar populasi telah kehilangan kepercayaan pada rezim selama 15 tahun terakhir.” Bandingkan dengan Venezuela, di mana intervensi AS menggulingkan Maduro, para analis seperti Kamran Matin dari University of Sussex melihat peluang serupa di Iran, meskipun sejarah kudeta 1953 membuat intervensi asing berisiko memicu backlash nasionalis.

Implikasi masa depan tetap tidak pasti. Rezim telah bertahan dari perang, sanksi, dan gejolak melalui kekuatan brutal dan pragmatisme, tapi jalan keluar kini semakin sempit. Ellie Geranmayeh dari European Council on Foreign Relations mencatat bahwa perubahan terbaik datang dari dalam: “Pemimpin Iran menghadapi momen berbahaya, tapi mereka tidak asing dengan kekacauan.” Sementara dukungan untuk Reza Pahlavi, putra shah yang diasingkan, muncul di kalangan diaspora dan domestik, oposisi tetap terpecah. Di tengah sanksi PBB yang diperbarui pada September lalu, yang membekukan aset dan menghentikan kesepakatan senjata, ekonomi Iran semakin rapuh, mendorong spekulasi tentang negosiasi nuklir baru atau bahkan transisi kekuasaan. Namun, seperti yang diamati Amnesty International, siklus kekerasan ini berisiko memperburuk pelanggaran hak asasi manusia, dengan ribuan cedera dan potensi eksekusi massal.
Pewarta : Setiawan Wibisono