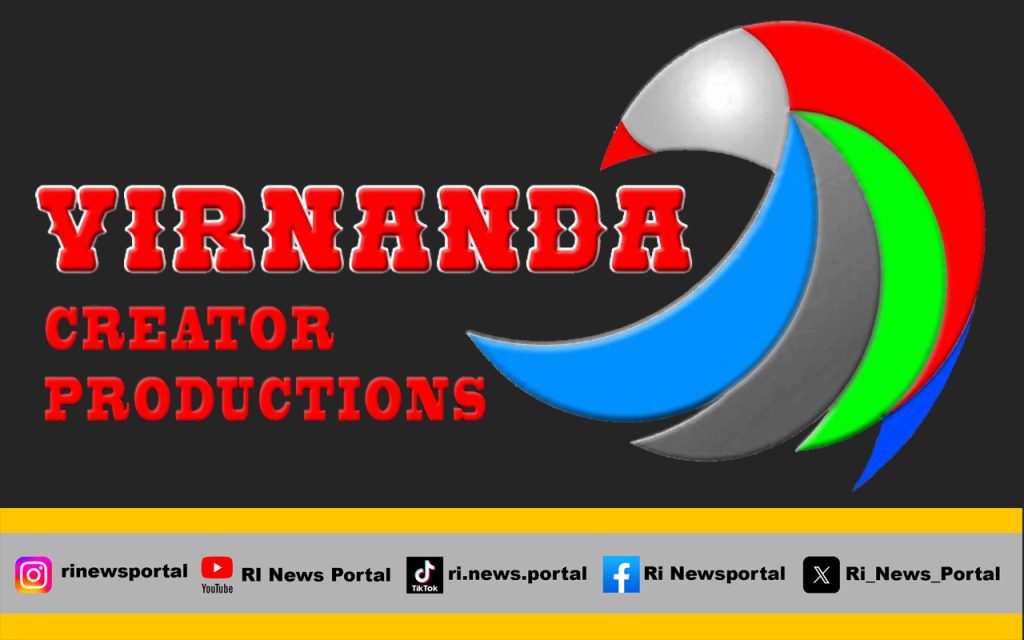RI News Portal. Padang, 17 Oktober 2025 – Di lereng bukit hijau Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan daun kelapa sawit yang sudah lama dikelola warga. Namun, di balik keindahan alam itu, bergema keluhan pilu: lahan warisan leluhur kini terancam direnggut oleh Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sukses Jaya Wood (SJW), perusahaan pengolahan kayu yang beroperasi di wilayah perbatasan. Sengketa ini, yang kembali mencuat pekan ini, bukan sekadar friksi administratif, melainkan panggilan mendesak atas keadilan bagi komunitas adat yang telah berpuluh tahun menggantungkan hidup pada tanah tersebut.
Advokat muda Edo Mandela, kuasa hukum perwakilan masyarakat Silaut, menyoroti inti persoalan: penerbitan HGU SJW dinilai cacat hukum sejak akarnya. “Penyerahan hak ulayat dilakukan oleh Ninik Mamak Lunang kepada perusahaan, tanpa persetujuan Ninik Mamak Silaut, padahal lahan sengketa jelas berada dalam teritori adat Silaut,” tegas Edo dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi. Fakta lapangan, menurutnya, tak terbantahkan: warga telah menggarap lahan untuk perkebunan sejak generasi sebelumnya, sementara HGU baru muncul belakangan tanpa proses konsultasi yang sah dengan pemangku adat asli.
Bayangkan seorang petani tua seperti Pak Rahman, yang tak disebut namanya di sini untuk alasan keamanan, berdiri di pinggir kebunnya yang kini dipagari kawat berduri. “Anak cucu saya lahir dan besar di sini. Sawit ini bukan cuma tanaman, tapi napas keluarga. Tiba-tiba, alat berat datang dan klaim ini milik perusahaan. Di mana hak kami?” ceritanya dengan suara parau, mewakili ratusan rumah tangga yang kini terjepit antara tradisi dan modernitas korporatif. Lahan seluas ribuan hektare, yang menjadi sumber mata pencaharian utama, kini menjadi medan pertempuran diam-diam antara hak ulayat dan kepentingan ekonomi.

Edo Mandela menekankan bahwa perjuangan ini bukanlah penolakan buta terhadap investasi, melainkan upaya memastikan lindung hukum dan moral bagi yang lemah. “Ini soal keadilan dan kesetaraan. Jika negara membiarkan praktik seperti ini—di mana administrasi perizinan mengorbankan rakyat kecil demi korporasi raksasa—maka akan lahir korban baru setiap hari,” ujarnya. Sebagai fondasi argumennya, Edo merujuk Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.” Bagi sang advokat, ayat konstitusi ini bukan sekadar kata-kata mati; ia adalah perisai konstitusional yang menegaskan hak masyarakat atas tanah sebagai sumber kehidupan, tak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk pemegang HGU.
Langkah konkret telah dirintis. Bersama relawan dari jaringan Tegak Lurus Prabowo dan kelompok tani Palas Merah BS3, tim hukum Edo telah menyusun strategi komprehensif: mulai dari pelaporan ke lembaga penegak hukum hingga pengaduan ke badan pengawas negara. Mereka juga mendesak penghentian sementara aktivitas perusahaan di lahan sengketa, hingga status kepemilikan lahan memperoleh kejelasan mutlak. “Kami tak ingin konflik eskalasi, tapi dialog harus adil—bukan monopoli narasi korporasi,” tambah Edo, yang dikenal sebagai pembela hak agraria di kawasan pesisir Sumatera Barat.
Respons dari otoritas setempat menambah harapan. Kapolda Sumatera Barat dikabarkan telah memerintahkan Kapolres Pesisir Selatan untuk menggelar audiensi darurat di ruangannya. Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah menampung aspirasi langsung dari warga Silaut, mencari solusi yang tak hanya menyelesaikan sengketa saat ini, tapi juga mencegah preseden buruk di masa depan. “Ini langkah awal yang positif. Polisi bisa jadi jembatan, asal tak terjebak birokrasi,” komentar Edo.
Dalam konteks lebih luas, kasus Nagari Silaut mencerminkan luka agraria yang menganga di Indonesia timur. Hak ulayat, yang diakui UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat 2, sering terpinggirkan oleh dinamika perizinan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan sosial. Para ahli hukum agraria, seperti yang dikutip dari studi terbaru Universitas Andalas, memperingatkan bahwa ketidakseimbangan ini bisa memicu instabilitas sosial, terutama di daerah adat seperti Minangkabau di Sumatera Barat. “Tanah bukan komoditas; ia adalah identitas. Mengabaikannya berarti merusak fondasi bangsa,” demikian salah satu temuan riset tersebut.
Upaya Edo Mandela dan kawan-kawannya menjadi simbol perlawanan yang inspiratif: advokat muda yang berdiri di garis depan, membela suara rakyat atas tanah mereka. Di Nagari Silaut, di mana sungai Sindang Alam menjadi saksi bisu batas wilayah, harapan kini bergantung pada keadilan yang tak lagi tertunda. Apakah audiensi mendatang akan membawa angin segar, atau sekadar hembusan sementara? Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti: perjuangan ini telah membangunkan kesadaran bahwa hak atas tanah adalah hak atas martabat manusia.
Pewarta : Sami S