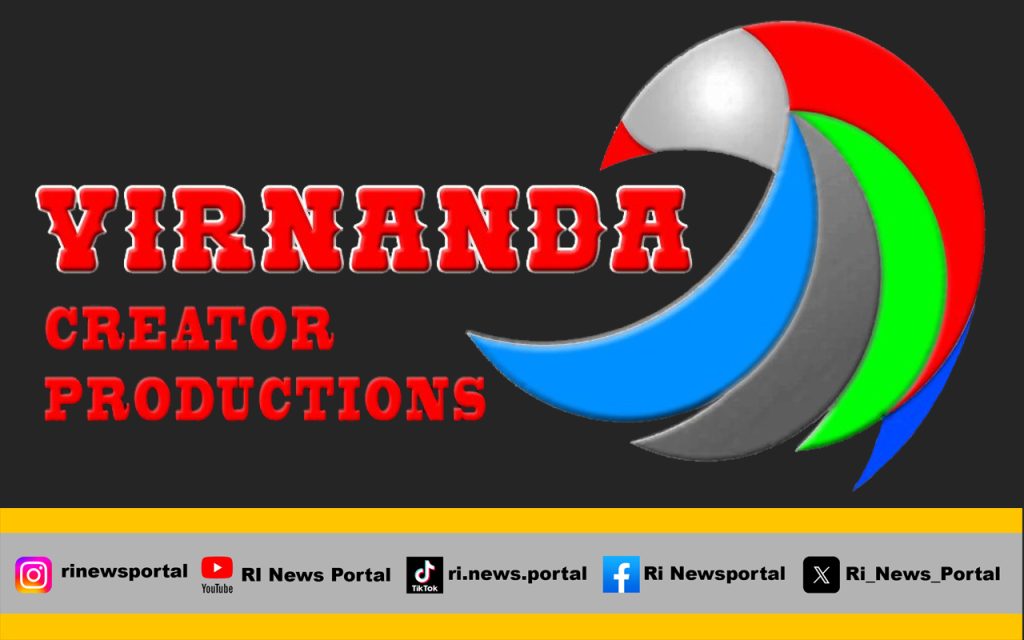RI News Portal. Wonogiri – Proses hukum atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang santri berinisial MMA, berusia 12 tahun, di Pondok Pesantren Santri Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, segera memasuki tahap persidangan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, di Pengadilan Negeri Wonogiri. Kasus ini menyoroti isu krusial perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis agama, di mana kekerasan fisik sering kali tersembunyi di balik tradisi disiplin internal.
Menurut Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, Murdiyanta Setya Budi, berkas perkara telah dilimpahkan dari Satreskrim Polres Wonogiri pada 30 Desember 2025. Kejaksaan telah melengkapi dokumen tersebut untuk diserahkan ke pengadilan, memastikan proses berjalan lancar. Dari empat anak yang semula ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, hanya dua yang akan diadili sebagai terdakwa. Alasan utamanya adalah dua anak lainnya berusia di bawah 12 tahun, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum. “Anak di bawah usia tersebut dikembalikan kepada orang tua mereka untuk pendampingan lebih lanjut,” ujar Budi dalam keterangannya pada Senin, 12 Januari 2026.

Agenda sidang pertama mencakup pembacaan dakwaan, dengan harapan bisa langsung dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Pendekatan ini diharapkan mempercepat proses, mengingat status terdakwa sebagai anak-anak yang memerlukan penanganan sensitif untuk menghindari trauma berkepanjangan. Kasus ini mengemuka setelah MMA, santri asal Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, ditemukan meninggal pada 15 Desember 2025. Pemeriksaan medis mengungkap luka lebam di berbagai bagian tubuh, termasuk dada, yang diduga akibat penganiayaan oleh sesama santri. Polisi awalnya mengamankan sembilan santri di bawah umur terkait dugaan pengeroyokan, sebelum mempersempitnya menjadi empat tersangka.
Dari perspektif hukum, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 170 ayat (2) KUHP, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menekankan prinsip restoratif justice bagi pelaku anak, di mana rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman penjara. Namun, kasus ini juga menggarisbawahi tantangan dalam menerapkan hukum perlindungan anak di Indonesia, di mana batas usia tanggung jawab pidana sering menjadi perdebatan etis dan legal. Secara akademis, pendekatan ini selaras dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB, yang menuntut negara untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses yudisial.
Baca juga : Penolakan Praperadilan Wakil Wali Kota Bandung: Affirmasi Prosedur Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi
Lebih luas lagi, insiden di Ponpes Santri Manjung bukanlah kasus terisolasi. Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat setidaknya 60 kasus kekerasan di lembaga pendidikan sepanjang 2025, dengan 358 korban dan 126 pelaku, termasuk di pondok pesantren. Tren ini mencerminkan masalah struktural, seperti kurangnya pengawasan eksternal dan budaya senioritas yang kerap membenarkan bentuk disiplin fisik. Di tingkat nasional, Kementerian Agama telah membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan di pesantren, meskipun implementasinya masih diuji di lapangan. Kasus-kasus serupa, seperti dugaan pelecehan di pesantren Jawa Timur baru-baru ini, semakin mendorong diskusi tentang reformasi kurikulum dan pelatihan pengasuh untuk memasukkan modul anti-kekerasan.
Sebagai respons langsung, Kementerian Agama telah melarang Ponpes Santri Manjung menerima santri baru untuk sementara waktu dan meminta perubahan struktur pengurusan. Saat ini, pemilik pondok, Eko Julianto, merangkap sebagai pengasuh, yang dianggap tidak ideal untuk pengawasan optimal. Jika rekomendasi ini tidak dipatuhi, ancaman penutupan permanen menggantung. Eko menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti, dengan rencana menyerahkan tugas pengasuhan kepada ustaz senior yang lebih berpengalaman, yang akan hadir penuh waktu di pondok. “Perubahan ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terstruktur,” katanya.
Kasus ini menjadi momentum bagi stakeholders pendidikan keagamaan untuk merefleksikan praktik internal mereka. Dengan pendekatan yang lebih holistik, termasuk integrasi psikologi anak dan mekanisme pelaporan independen, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir. Persidangan mendatang tidak hanya akan menentukan nasib terdakwa, tetapi juga mengukur komitmen sistem hukum Indonesia dalam melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan di ruang pendidikan.
Pewarta : Nandar Suyadi