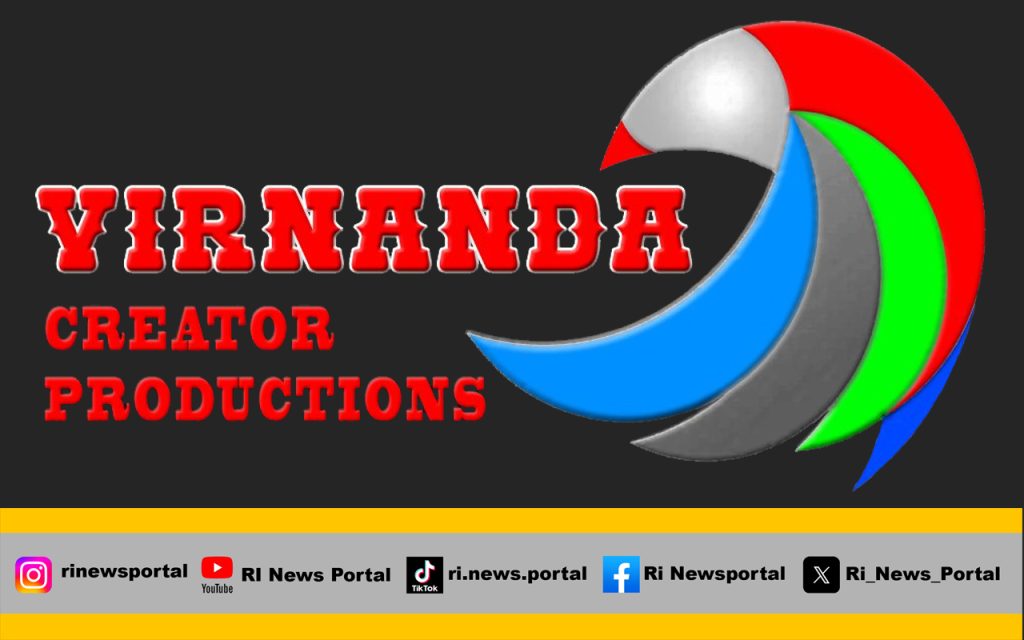RI News Portal. Washington 01 November 2025 – Dalam konteks geopolitik yang semakin tegang, kebijakan militer suatu negara tidak hanya mencerminkan strategi pertahanan, tetapi juga nilai-nilai sosial dan etika yang mendasarinya. Kebijakan terbaru Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengenai prajurit transgender, yang diumumkan melalui memo internal pada 8 Oktober 2025, menjadi contoh nyata bagaimana isu identitas gender dapat mengganggu prinsip kesetaraan dalam institusi bersenjata. Kebijakan ini, yang melanjutkan eksekutif order Presiden Donald Trump, memungkinkan komandan untuk membatalkan keputusan dewan pemisahan yang mendukung retensi prajurit transgender, serta mewajibkan penampilan seragam sesuai jenis kelamin lahir. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan tersebut terhadap kesiapan militer, hak asasi manusia, dan dinamika rekrutmen, dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi keamanan dan sosiologi militer.
Sejak 2016, militer AS telah mengalami pergeseran signifikan dalam kebijakan transgender. Di bawah administrasi Obama, prajurit transgender diizinkan bertugas secara terbuka, dengan dukungan medis untuk transisi gender, berdasarkan prinsip bahwa identitas gender tidak menghambat kinerja. Namun, tweet Trump pada 2017 yang melarangnya memicu perdebatan nasional, yang sempat dibalikkan oleh Biden pada 2021. Kembalinya Trump pada 2025 membawa gelombang baru pembatasan: eksekutif order Januari 2025 menyatakan disforia gender sebagai “tidak kompatibel” dengan standar militer, diikuti memo Februari yang menghentikan perekrutan transgender dan membatasi perawatan medis.
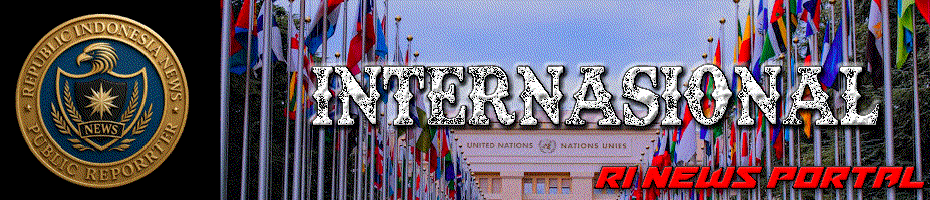
Puncaknya adalah memo Oktober 2025 dari Wakil Menteri Anthony Tata, yang secara eksplisit memungkinkan override komandan atas dewan pemisahan—sebuah pelanggaran terhadap tradisi independensi dewan sejak 1948. Selain itu, prajurit transgender diwajibkan hadir di sidang dengan seragam sesuai jenis kelamin lahir; ketidakpatuhan dapat dianggap sebagai bukti pemisahan. Data internal Pentagon memperkirakan sekitar 1.000-1.500 prajurit terdampak, banyak di antaranya telah bertugas lebih dari 10 tahun di posisi kritis seperti intelijen dan operasi khusus.
Dari sudut pandang keamanan nasional, kebijakan ini berpotensi merusak efektivitas militer AS. Studi dari Rand Corporation (2016, diperbarui 2024) menunjukkan bahwa inklusi transgender tidak meningkatkan biaya medis secara signifikan (kurang dari 0,1% anggaran kesehatan militer) dan justru meningkatkan retensi talenta. Prajurit transgender sering kali memiliki tingkat pendidikan dan spesialisasi lebih tinggi, berkontribusi pada unit-unit elit. Logan Ireland, sersan utama Angkatan Udara dengan 15 tahun pengalaman, menggambarkan kebijakan ini sebagai “pengkhianatan” terhadap pengakuan militer atas identitasnya selama 13 tahun, yang kini terancam oleh kewajiban seragam yang “seperti kostum”. Hilangnya prajurit seperti Ireland bisa menciptakan kekosongan operasional yang memakan waktu hingga satu dekade untuk diisi, terutama di tengah krisis rekrutmen militer AS yang mencapai titik terendah sejak 1973 (hanya 23% target tercapai pada 2024).
Lebih lanjut, Menteri Pertahanan Pete Hegseth membenarkan kebijakan ini sebagai upaya “meningkatkan daya tembak” dengan menghilangkan “kebingungan gender”. Namun, kritik dari pakar seperti Emily Starbuck Gerson dari kelompok advokasi SPARTA Pride menyoroti bahwa ini justru bertentangan dengan doktrin militer berbasis meritokrasi. Penelitian di Journal of Military Ethics (2023) oleh Prof. Aaron Belkin menemukan bahwa unit inklusif transgender memiliki kohesi lebih tinggi daripada unit homogen, karena mendorong adaptasi dan empati—kualitas esensial dalam perang asimetris modern.
Secara etis, kebijakan ini menimbulkan pelanggaran potensial terhadap Konvensi Hak Asasi Manusia PBB, khususnya Pasal 7 tentang larangan diskriminasi. Pengacara militer Priya Rashid, yang mewakili ratusan kasus pemisahan, menyebutnya sebagai “subversi keadilan”, di mana prajurit transgender menerima proses hukum lebih sedikit daripada mereka yang terlibat dalam pelanggaran serius seperti kerusuhan Capitol 2021—yang justru dipertahankan dewan. Mahkamah Agung AS pada Mei 2025 mengizinkan penegakan sementara, tetapi panel banding D.C. Circuit pada April menunjukkan keraguan konstitusional, memerintahkan kelanjutan perawatan medis sambil litigasi berlangsung.

Implikasi global tidak kalah penting. Sebagai pemimpin aliansi NATO, kebijakan AS memengaruhi norma internasional. Kanada dan Inggris, yang telah sepenuhnya inklusif sejak 2017, melaporkan peningkatan rekrutmen 15% di kalangan minoritas gender. Sebaliknya, pembatasan AS berisiko mengisolasi militer dari talenta beragam, memperlemah posisi strategis melawan rival seperti China, yang memanfaatkan narasi “keunggulan budaya” dalam propaganda.
Untuk mengatasi dilema ini, Pentagon disarankan merevisi kebijakan dengan model “grandfather clause”—melindungi prajurit transgender yang sudah bertugas berdasarkan bukti kontribusi individu, bukan label administratif. Kongres juga dapat mendorong audit independen oleh GAO untuk menilai dampak rekrutmen. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal gender, melainkan ujian bagi militer AS: apakah ia tetap sebagai institusi meritokratis yang adaptif, atau regresi ke era eksklusif yang merugikan keamanan nasional.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH