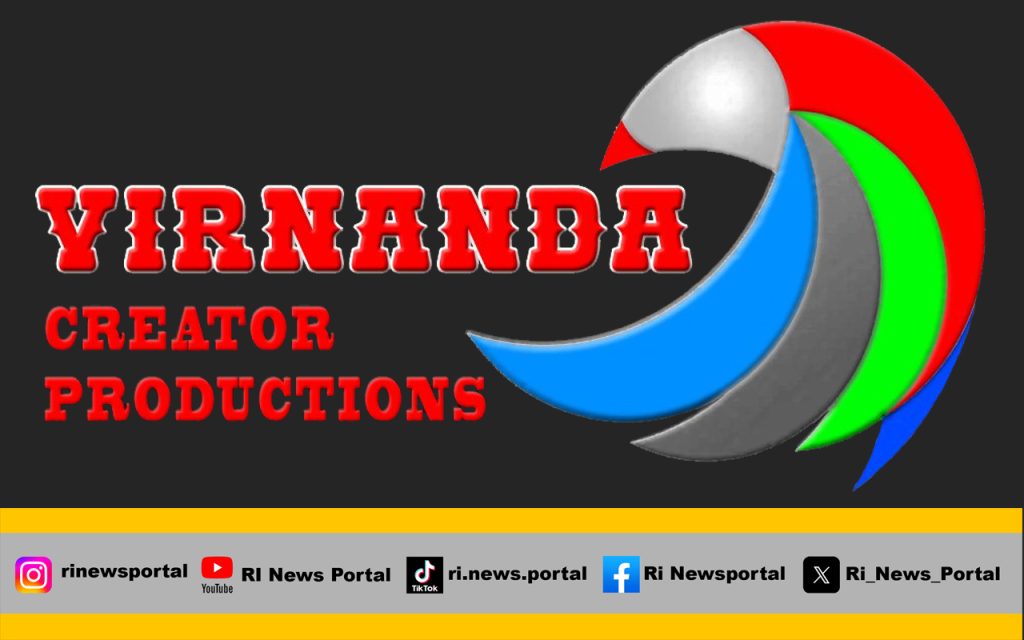RI News Portal. Takalar, Sulawesi Selatan – 6 September 2025 – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan pedesaan di Kabupaten Takalar, sebuah insiden kekerasan telah menjadi katalisator perdebatan publik tentang efektivitas sistem peradilan Indonesia. Rasul Dg Sore, seorang warga berusia 48 tahun asal Tamala’lang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, menjadi korban dugaan pengeroyokan yang menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis. Kejadian ini, yang terjadi pada malam 31 Agustus 2025, tidak hanya mengungkap potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat, tetapi juga menguji komitmen kepolisian dalam menegakkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi.
Rasul, yang ditemui di kediamannya dengan bekas luka memar masih terlihat di wajah dan tubuhnya, menceritakan kronologi peristiwa dengan nada getir. Ia awalnya mendatangi kawasan perumahan di Desa Bontomajannang, Kelurahan Bontolebang, untuk memeriksa progres pembangunan rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mengonsumsi minuman keras tradisional jenis ballo. “Saya ditawari minum, tapi saya tolak. Hanya mencicip sedikit sambil bercanda. Tiba-tiba, seorang sopir yang dikaitkan dengan aparat kepolisian—namanya belum saya ketahui—langsung memukul saya hingga jatuh,” ujar Rasul, suaranya bergetar mengenang momen itu. Tak berhenti di situ, sekitar delapan hingga sembilan orang lainnya bergabung, memukul, mencekik, dan menahan tangannya hingga ia hampir kehilangan kesadaran.

Insiden ini bukan sekadar pertengkaran biasa; ia mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di masyarakat lokal. Rasul segera melaporkan kejadian ke Polsek Bontolebang dengan nomor laporan LP/B/85/VIII/2025/SPKT/Sek Galut/Res Takalar/Polda Sulsel. Dalam laporannya, ia secara spesifik menyebut nama-nama terduga pelaku: Dg Opa, Dg Sikki, Dg Bella, Dg Sarro, Dg Nnri, serta dua orang lainnya yang identitasnya belum teridentifikasi. Menariknya, setelah kejadian, Kanit Reskrim Polsek sempat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Namun, kehadiran aparat justru dianggap korban sebagai faktor yang memperburuk situasi, karena mereka tidak langsung mengamankan pelaku meski korban dan pelaku masih berada di lokasi.
Saksi mata utama, Daeng Ngimba, yang menemani Rasul saat itu, memberikan kesaksian yang menguatkan narasi korban. “Saya melihat langsung bagaimana korban dipukul dan dicekik lehernya hingga hampir pingsan. Bahkan, pelaku sempat mendorong saya dan mengejar dengan kursi plastik,” katanya, menekankan elemen ancaman yang meluas. Kesaksian ini menambah bobot pada tuntutan korban agar polisi bertindak cepat, terutama mengingat potensi hilangnya bukti atau pelarian pelaku.
Baca juga : Tragedi Waduk Gajah Mungkur: Dua Pelajar Tewas Tenggelam
Pihak Polsek Bontolebang, melalui Kanitnya, membenarkan adanya laporan tersebut. “Benar ada laporan dengan nomor itu. Saat ini, kami masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya secara singkat, tanpa memberikan detail lebih lanjut tentang kemajuan penyelidikan. Namun, respons ini dirasa korban sebagai tanda ketidaktegasan. “Pelaku masih berkeliaran bebas, sementara surat hasil visum et repertum pun belum keluar. Saya harap polisi segera bertindak dan transparan,” tegas Rasul, menyuarakan kekhawatiran yang sering muncul dalam kasus-kasus serupa di daerah pedesaan.
Investigasi independen oleh jurnalis media online seperti Muh. Syibli dan Gibran mengungkap pola penanganan yang terkesan lamban. “Korban sudah menyebut nama-nama secara jelas, tapi belum ada pengamanan. Di kasus sebelumnya, polisi bertindak cepat. Apakah ada perbedaan aturan sekarang?” tanya Syibli, menyoroti inkonsistensi yang bisa merusak kepercayaan publik. Kritik ini diperkuat oleh keluarga korban, yang mendesak intervensi tingkat tinggi. “Kami minta Kapolri, Kapolda Sulsel, dan Kapolres Takalar turun tangan. Kami hanya ingin keadilan, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” kata perwakilan keluarga, menggarisbawahi aspirasi masyarakat untuk reformasi penegakan hukum.
Kasus ini menyentuh inti prinsip hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah resmi jika situasi mendesak, dengan surat menyusul kemudian. Dalam konteks ini, dengan identitas pelaku yang sudah disebutkan dan kehadiran mereka di TKP, aparat seharusnya bisa melakukan pengamanan awal untuk mencegah pelarian atau penghilangan bukti. Analisis ini mengingatkan pada studi-studi kriminologi yang menunjukkan bahwa keterlambatan respons polisi sering kali berkorelasi dengan rendahnya tingkat resolusi kasus kekerasan di wilayah rural, di mana faktor sosial-budaya seperti hubungan patron-klien antara warga dan aparat bisa memengaruhi proses.

Lebih luas, insiden di Takalar ini menjadi cermin dari tantangan nasional dalam membangun kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Di era digital di mana informasi menyebar cepat melalui media sosial, ketidaktransparanan bisa memicu spekulasi dan polarisasi masyarakat. Kasus ini bukan hanya tentang satu korban, melainkan ujian bagi kepolisian untuk membuktikan komitmennya dalam memberikan rasa aman, terutama bagi warga biasa yang sering merasa termarjinalkan. Sebagai masyarakat yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan narasi penegakan hukum yang inklusif, di mana setiap laporan ditangani dengan kecepatan dan ketelitian yang sama, tanpa memandang status sosial pelaku atau korban.
Pembaca diundang untuk mengikuti perkembangan kasus ini melalui pembaruan eksklusif di platform kami, di mana kami akan terus memantau respons aparat dan implikasi sosialnya. Jika Anda memiliki informasi tambahan, hubungi redaksi secara anonim untuk mendukung transparansi bersama.
Pewarta : Yosep Sukardi