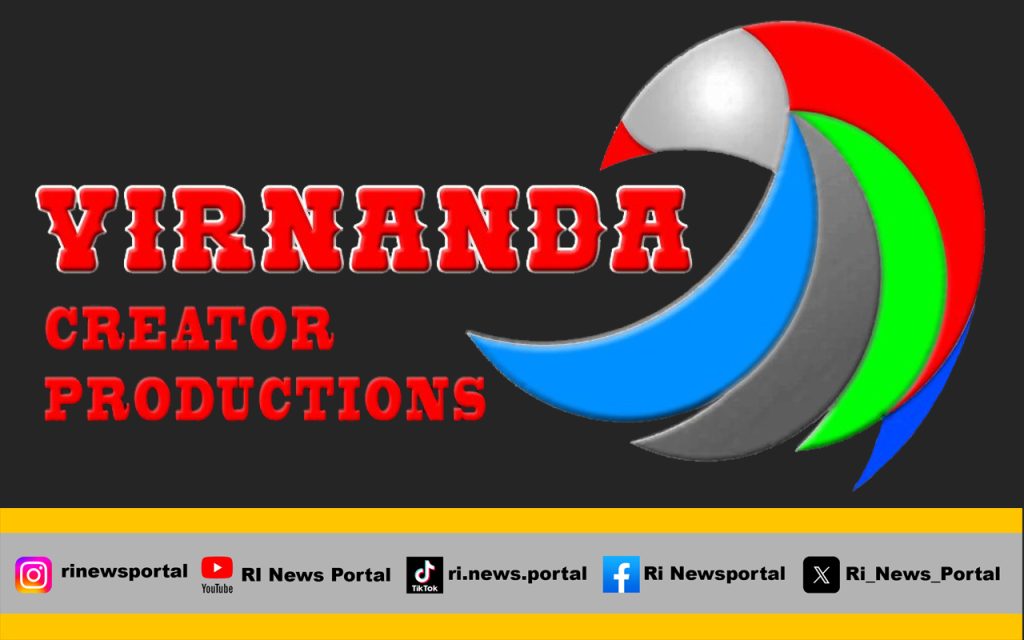RI News Portal. Jakarta, 9 November 2025 – Dalam sebuah pergeseran yang menandai evolusi kreatif di perfilman Indonesia, film Pangku akhirnya menyapa layar lebar bioskop nasional sejak Kamis lalu, 6 November 2025. Karya ini bukan sekadar debut Reza Rahadian sebagai sutradara film panjang, melainkan sebuah manifesto visual yang menyelami lapisan-lapisan ketidakadilan gender dan dinamika ekonomi informal di wilayah pesisir Pantura (Pantai Utara Jawa). Diproduksi oleh Gambar Gerak Film, Pangku hadir sebagai respons artistik terhadap realitas yang sering kali terpinggirkan dalam narasi sinematik mainstream, mengajak penonton untuk merenungkan biaya emosional dari kelangsungan hidup di tengah arus kapitalisme pinggiran.
Sebelum memasuki sirkulasi domestik, Pangku telah mengukir jejak internasional di Busan International Film Festival (BIFF) 2025, di mana pemutaran perdananya disambut dengan applaus panjang. Kritikus di sana memuji bagaimana film ini mengintegrasikan elemen hangat dari hubungan interpersonal dengan kritik tajam terhadap eksploitasi struktural, menjadikannya salah satu sorotan Asia Tenggara yang menonjol. “Ini bukan hanya cerita tentang perempuan; ini tentang bagaimana sistem ekonomi merangkul dan meremukkan mereka secara bersamaan,” tulis seorang reviewer dari jurnal film Korea Selatan, menyoroti bagaimana Pangku berhasil menyatukan intimasi domestik dengan analisis sosial yang mendalam.
Dipimpin oleh trio pemeran utama yang brilian—Claresta Taufan sebagai Sartika, Christine Hakim sebagai Maya, dan Fedi Nuril sebagai Hadi—film ini membangun lapisan naratif yang kaya akan nuansa emosional. Claresta, dalam peran breakout-nya, menghidupkan Sartika sebagai perwujudan resiliensi yang rapuh: seorang ibu hamil yang meninggalkan desa asalnya, didorong oleh visi kabur tentang masa depan yang lebih cerah bagi anak yang dikandungnya. Di perantauan yang tak kenal ampun, ia bertemu Maya, seorang pemilik kedai kopi yang karismatik namun ambigu, yang menawarkan tempat berlindung sekaligus jebakan halus. Christine Hakim, dengan kedalaman aktingnya yang legendaris, memerankan Maya sebagai figur maternal yang retak—seorang penyintas yang mereproduksi siklus penindasan demi bertahan.

Inti konflik Pangku terletak pada praktik “kopi pangku” itu sendiri, sebuah fenomena budaya-ekonomi di kedai-kedai pesisir di mana pelayan perempuan melayani tamu dengan kontak fisik yang menjijikkan intimasi. Setelah melahirkan, Sartika terperangkap dalam jaringan ini, di mana kasih sayang Maya berubah menjadi paksaan halus untuk bergabung dalam ritme harian yang merendahkan. Naskah, yang ditulis Reza Rahadian bersama Felix K. Nesi—penerima SEA Write Award 2020—menavigasi dilema ini dengan subtilitas, menghindari sensasionalisme demi eksplorasi psikologis yang teliti. Produksi Arya Ibrahim dan Gita Fara memastikan bahwa visual film ini, dengan sinematografi yang menangkap debu jalanan Pantura dan hembusan angin laut, menjadi metafora bagi ketidakpastian hidup para karakternya.
Titik balik naratif datang melalui pertemuan Sartika dengan Hadi, sopir truk distributor ikan yang digambarkan Fedi Nuril dengan kelembutan yang menyentuh. Hadi bukan pahlawan romantis konvensional; ia adalah cerminan dari maskulinitas yang terpinggirkan, yang tumbuh rasa cintanya dari momen-momen sederhana seperti berbagi cerita di tepi dermaga. Hubungan ini menjadi katalisator bagi Sartika untuk mempertanyakan pilihan-pilihannya: apakah kebahagiaan sejati mungkin lahir dari cinta yang organik, atau apakah ia selamanya terikat pada kontrak tak tertulis dari kemiskinan struktural? Pertanyaan ini, yang bergema sepanjang durasi film, mengundang diskusi akademis tentang agensi perempuan dalam konteks feminisme interseksional, di mana kelas dan gender saling bertautan.
Baca juga : KPK Perluas Penyidikan ke Proyek Monumen Reog Ponorogo di Tengah Skandal Suap Bupati Sugiri Sancoko
Dari perspektif akademis, Pangku berkontribusi pada diskursus sinema Indonesia kontemporer dengan mengadopsi pendekatan realisme sosial yang menyerupai karya-karya Abbas Kiarostami atau Asghar Farhadi, di mana narasi pribadi menjadi lensa untuk mengkritik ketidakadilan sistemik. Reza Rahadian, yang selama dua dekade mendominasi layar sebagai aktor pemenang Piala Citra, membawa pengalaman itu ke balik kamera dengan visi yang matang. Inspirasi film ini berakar pada pengamatan pribadinya di Pantura sekitar 2020, di mana ia menyaksikan kedai-kedai kopi sebagai ruang hibrida: tempat pertemuan sosial sekaligus arena eksploitasi. “Saya ingin cerita ini bukan hanya mengharukan, tapi juga memprovokasi—agar penonton melihat diri mereka dalam cermin yang retak ini,” ujar Reza dalam wawancara eksklusif pasca-premiere, menekankan komitmennya terhadap narasi yang autentik.
Lebih dari hiburan, Pangku muncul sebagai intervensi budaya yang relevan di tengah diskusi nasional tentang perlindungan pekerja informal dan pemberdayaan perempuan pedesaan. Dengan runtime yang padat dan akhir yang ambigu—yang meninggalkan Sartika di persimpangan antara penerimaan dan pemberontakan—film ini menantang penonton untuk melampaui empati pasif menuju aksi reflektif. Di tahun 2025, di mana sinema Indonesia semakin berani mengeksplorasi isu marginal, debut Reza Rahadian ini bukan hanya patut ditonton; ia adalah dokumen esensial tentang bagaimana cinta dan perjuangan bisa menjadi bentuk perlawanan yang paling intim. Bagi para sarjana film, Pangku menjanjikan ruang analisis yang subur, mengingatkan bahwa seni terbaik lahir dari gesekan antara hati yang rapuh dan dunia yang tak kenal belas kasihan.
Pewarta : Vie