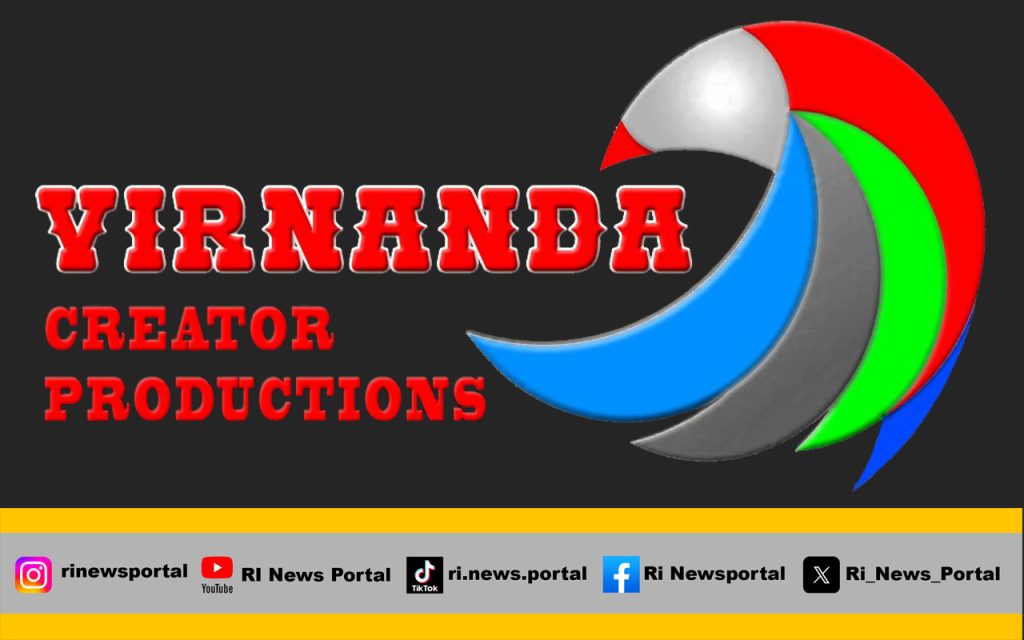RI News Portal. Bogor, 14 Juli 2025 – Sengkarut hukum mengenai pernikahan ilegal kembali menjadi sorotan publik setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Cibinong hanya menuntut satu tahun penjara terhadap terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 279 ayat 2 KUHP. Kasus ini mencuat setelah pelapor, Ibu Dermawan Simbolon, memperjuangkan keabsahan pernikahan dan keutuhan keluarganya melalui jalur hukum.
Pernikahan dalam konteks hukum Indonesia mengandung dua dimensi utama, yakni legalitas keagamaan dan administrasi kependudukan. Sebuah pernikahan yang sah bukan hanya harus memenuhi syarat menurut agama masing-masing, tetapi juga tercatat secara resmi dalam dokumen negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya.
Namun demikian, perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan ilegal seringkali menimbulkan ambiguitas di masyarakat. Pernikahan siri, walau sah menurut agama, tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Sementara itu, pernikahan ilegal, seperti yang diduga dalam perkara ini, melibatkan pelanggaran hukum substantif—yakni pernikahan yang dilakukan meski salah satu pihak masih terikat pernikahan sah lain tanpa adanya izin atau perceraian resmi.

Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan pernikahan kedua tanpa terlebih dahulu menyelesaikan ikatan pernikahan pertamanya. Perbuatan ini diduga melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menikah dengan seseorang padahal diketahui bahwa perkawinan itu menjadi batal karena halangan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
Usai sidang, Ibu Dermawan Simbolon menyatakan kekecewaannya atas tuntutan ringan dari JPU. “Ancaman hukumannya bisa sampai tujuh tahun, tapi kenapa hanya dituntut satu tahun? Ini tidak adil. Kami ingin keadilan ditegakkan secara murni,” ucapnya dengan nada emosional.
Senada dengan itu, kuasa hukum pelapor, Bangun Simbolon, menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak sebanding dengan bukti dan fakta persidangan. “Kami mengikuti seluruh proses, dari pembacaan dakwaan hingga keterangan ahli. Bukti menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui ada halangan hukum yang sah, namun tetap melangsungkan pernikahan,” ujarnya.
Menurut Bangun Simbolon, apabila tuntutan dijatuhkan selama tiga tahun, hal itu masih bisa diterima dalam kerangka logika hukum. Namun tuntutan hanya satu tahun dianggap terlalu ringan dan menimbulkan kecurigaan. “Tuntutan ini mencederai rasa keadilan, baik secara normatif maupun sosiologis,” tegasnya.
Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis hukum, tetapi juga menggugah perhatian publik terhadap moralitas hukum, integritas institusi peradilan, serta kepercayaan masyarakat pada sistem hukum nasional. Pertanyaan kritis pun mencuat: apakah lembaga hukum mampu menjadi penjaga nilai dan norma publik, atau justru rentan terhadap kompromi yang melemahkan keadilan substantif?
Akademisi hukum keluarga dari Universitas Indonesia, Dr. Sri Atmawati, SH, MH, menekankan bahwa kejelasan penerapan hukum dalam kasus pernikahan dengan halangan hukum sangat penting demi menjamin kepastian hukum. “Pasal 279 KUHP mengandung prinsip perlindungan terhadap status hukum seseorang dalam perkawinan. Jika ketentuan ini tidak ditegakkan secara tegas, maka akan muncul preseden buruk dan potensi pelecehan terhadap institusi perkawinan yang sah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dalam kasus semacam ini, tuntutan ringan dapat mengindikasikan lemahnya pendekatan keadilan restoratif maupun retributif, terutama ketika korban merasa dirugikan secara sosial, emosional, dan hukum.
Pihak keluarga pelapor kini berharap majelis hakim dapat mengambil keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mempertimbangkan seluruh bukti serta fakta persidangan secara objektif dan berimbang. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa hukum perdata dan pidana dalam ranah perkawinan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan moral masyarakat Indonesia.
Putusan dalam perkara ini kelak akan menjadi cerminan, apakah sistem hukum Indonesia tetap konsisten menegakkan supremasi hukum atau justru memberi ruang pada praktik kompromistik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Pewarta : Moh Romli